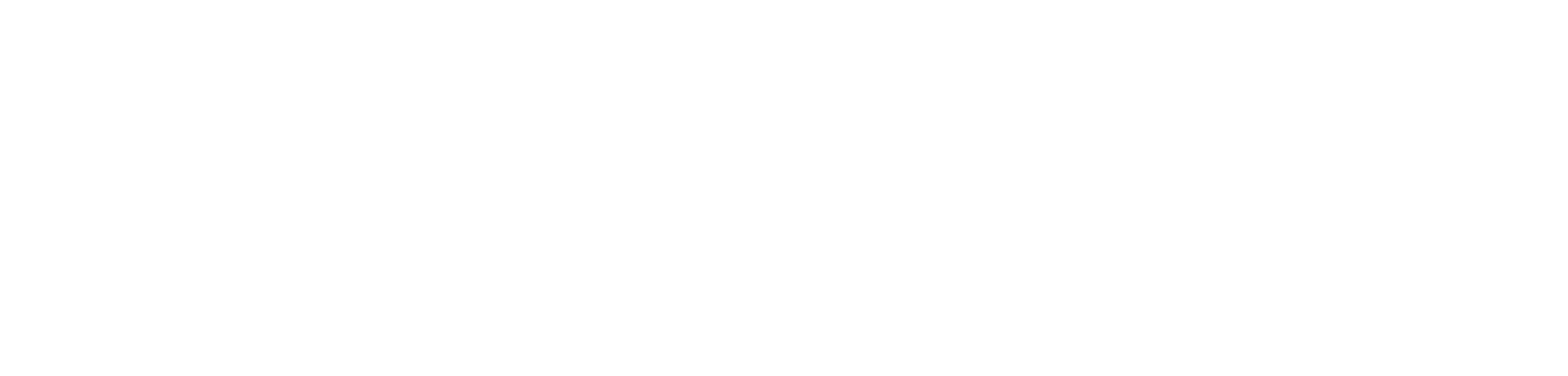Oleh Y Budi Widianarko
JUDUL tulisan ini sengaja meminjam diktum Rene Descartes "aku berpikir, maka aku ada" (cogito ergo sum). Dalam kemelimpahan informasi saat ini, penyangkalan adalah modal eksistensi pribadi dan kelompok yang bermuara pada saling asing antar kelompok-kelompok berbeda. Selain hoax yang disebut sebagai kanker demokrasi, kemelimpahan infonnasi digital memicu wabah penyakit lain yang tak kalah gawat, yaitu "kacamata kuda" alias penyangkalan.
Memerangi hoax tentu saja suatu kebijakan yang penting untuk menyelamatkan demokrasi. Ada penyakit lain akibat kemudahan akses baik mengunggah maupun mengunduh informasi secara digital, yaitu pembentukan sikap penyangkalan oleh seseorang terhadap berita yang tidak sesuai dengan pandangannya.
Penyangkalan itu tidak terjadi sesaat, tetapi melalui sebuah proses baik disadari maupun tidak disadari oleh subjek. Proses pembentukan penyangkalan melibatkan interaksi antara penyedia dan subjek penerima atau pencari informasi.
Sebagai penyakit, penyangkalan tidak kalah serius daripada hoax. Jikalau hoax dianggap merusak tatanan demokrasi dengan memproduksi kebohongan, penyangkalan memperlebar jurang antarkelompok yang berbeda pendapat hingga mengarah pada kondisi saling asing. Jika hal itu dibiarkan berlangsung terus, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik antarkelompok berkepanjangan.
Akar dari penyangkalan adalah ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang ketika mendapati informasi yang bertolak belakang dengan tata nilai dan keyakinannya. Ketika diperhadapkan dengan informasi atau data yang bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya (cognitive dissonance), seseorang dipaksa mengambil satu dan dua pilihan yang tidak mengenakkan.
Pilihan pertama, mempertahankan keyakinannya dan menyangkal informasi atau data yang diterima. Pilihan kedua, mengubah keyakinan dengan risiko harus kembali mengevaluasi cara pandang, pilihan, dan bahkan karaktemya.
Penyangkalan salah satu sikap yang diadopsi oleh seseorang yang mengalami cognitive dissonance untuk mengendalikan perasaan tidak nyamannya. Penyangkalan bisa terjadi dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam perdebatan tentang perubahan iklim, misalnya, muncul pula fenomena penyangkalan (baca: Requiem for A Species oleh Clive Hamilton, 2010). Makin melimpah bukti ilmiah bahwa pemanasan global diakibatkan oleh ulah manusia, temyata tidak membuat para penyangkal mengakomodasi fakta-fakta ilmiah itu.
Mereka malah kian keras menyerang para peneliti iklim, aktivis lingkungan, serta siapa saja yang menerima bukti pemanasan global sebagai fenomena akibat ulah manusia. Mereka justru berdalih, para peneliti iklim sengaja mengarang hasil risetnya demi terus mendapatkan dana; para peneliti yang bersuara di luar arus utama dibungkam, dan pemerintah berada di bawah tekanan para aktivis lingkungan.
Para penyangkal itu menjalankan sebuah metode yang disebut oleh pemikir Irlandia CS Lewis penulis The Chronicles of Narnia sebagai bulverism. Metode itu dijalankan dengan menglindari perlunya pembuktian benar salahargumen yang diajukan pihak lawan, melainkan langsung mengecap pendapat mereka itu salah, dan kemudian berusaha menjelaskan mengapa pihak lain bisa punya pandangah keliru.
Ketika bukti aktivitas dan gaya hidup manusia sebagai penyebab pemanasan global tambah banyak, penolakan para penyangkal justru menguat. Mereka melampiaskan kegusaran melalui surat pembaca di koran, blog, dan forum daring. Para penyangkal menyerang semua pihak yang berbeda keyakinan dan pandangan. Mereka akhirnya membentuk suatu kalangan sendiri, dan bahkan punya konferensi sendiri.
Dalam konferensi mereka berjumpa, saling menguatkan dan meyakinkan diri bahwa mereka memiliki pengetahuan (kebenaran) yang hebat. Dan dunia perlu mendengar mereka. Singkatnya, burung berbulu sama berkumpul jadi satu.
Fenomena penyangkalan itulah yang kita temui dalam media sosial hari-hari ini, terutama dalam perdebatan menyangkut politik. Para pihak yang berseberangan pandangan menghasilkan, mengunggah, mengunduh, dan mengunyah informasi demi memuaskan kelompoknya sendiri.
Akibatnya, sebuah paradoks terjadi. Media sosial yang merupakan ruang ekspresi bagi semua pihak malah menyempit dan hanya menghadirkan segelintir "kutub" kebenaran. Suatu pihak pasti akan menyangkal berita, informasi, data, dan fakta yang diunggah pihak lain, karena meyakini semua itu hanya dipakai untuk memperkuat posisi pihak lawan.
Yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa media sosial selaku wahana penyedia informasi turut berperan penting dalam mengukuhkan penyangkalan. Akibatnya, proses saling asing antarwarga yang memiliki tata nilai dan keyakinan yang berbeda makin diperparah.
Jika proses saling sangkal kita biarkan terus berlangsung, akan terjadi kondisi saling asing yang kian parah. Kelompok warga yang berbeda keyakinan dan pandangan politik bakal terpisahkan oleh sebuah ruang kosong yang makin hari tambah lebar. Bisa diduga, pada titik tertentu rajutan kebangsaan kita akan terkoyak. Kalau sudah begitu, kita dipaksa kembali menoleh ke pendidikan. Kita hams mengusahakan proses pendidikan di semua aras tidak menanamkan sikap “kacamata kuda".
Y. Budi Widianarko, Guru Besar Unika Soegijapranata Semarang
Sumber : Suara Merdeka 4 Desember 2017, hal. 4, E-paper Suara Merdeka, http://www.suaramerdeka.com