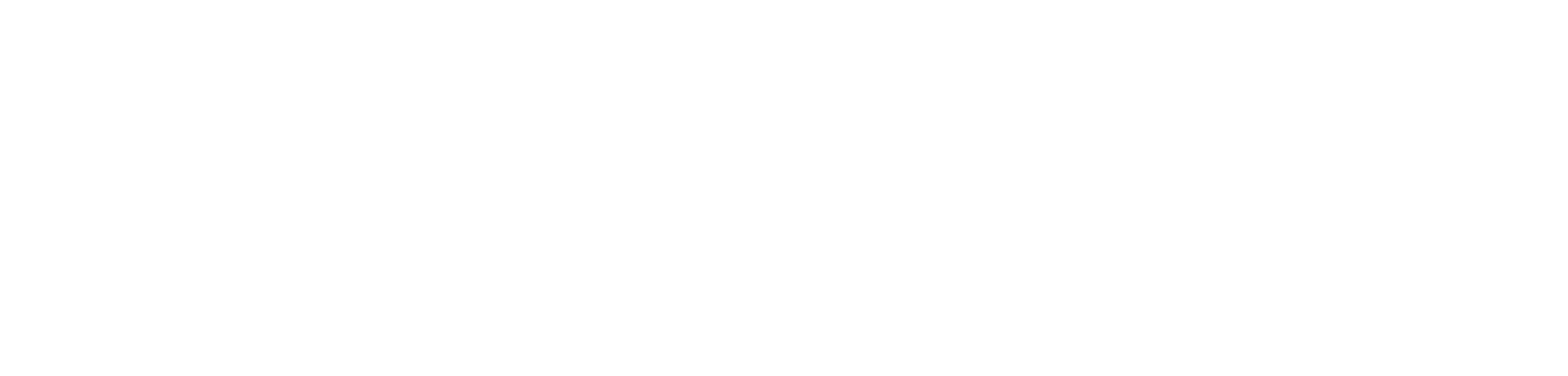Oleh Budi Widianarko
BELUM lama ini pendiri sekaligus Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) Klaus Schwab dan Thierry Malleret meluncurkan sebuah buku yang berjudul COVID-19: The Great Reset. Dalam buku itu, kedua penulis menyebut pandemi Covid- 19 adalah sebuah gugahan (wake-up call) dan mengajak kita berefleksi tentang bagaimana menjalankan pembangunan dengan cara baru, yaitu pembangunan yang tidak hanya demi kemajuan ekonomi manusia, tetapi sekaligus menjaga berkelanjutan alam.
Untuk itu seluruh dunia perlu menekan tombol reset agar manusia memulai cara menjalankan kehidupan yang baru. Dengan kata lain diperlukan paradigma pembangunan ekonomi yang baru atau berbeda dari yang sudah dijalankan selama ini.
Indonesia tentu saja tidak terbebas dari kebutuhan untuk menyesuaikan jika tidak mengubah-paradigma pembangunan ekonominya. Diakui atau tidak, dalam soal keberlanjutan- ruang untuk optimisme memang masih sempit. Wajah pembangunan Indonesia masih terus diwarnai tarik-menarik antara gairah untuk bertumbuh dan keberlanjutan tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19 ini.
Sebut saja, ketika beberapa lembaga international – seperti OECD dan Bank Dunia -menurunkan angka ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke kisaran minus 3% akibat cekaman pandemi Covid-19 maka muncullah suasana keterdesakan dan ketergesaan (desperate) untuk pulihnya perekonomian. Para ekonom segera saja menawarkan sejumlah kiat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, senada dengan seruan Great Reset, di Indonesia juga muncul pandangan yang mengingatkan pentingnya merumuskan normal baru perekonomian pascapandemi Covid-19. Ada ekonom yang berpendapat bahwa resesi akibat pandemi bisa menjadi momentum seleksi sektor ekonomi yang menyumbang pada perbaikan kualitas lingkungan serta adopsi teknologi. Tantangannya adalah menemukan paradigma pembangunan ekonomi yang mampu menyeimbangkan antara dorongan untuk perekonomian yang terus tumbuh dan keberlanjutan?
Catatan Sejarah
Semangat untuk selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bertitik pangkal dari gairah konsumsi manusia. Catatan sejarah peradaban manusia menunjukkan itu secara gamblang. Kajian material footprint (jejak material) mengungkapkan bahwa pada zaman Batu Baru (Neolithic) – sekitar 11000 tahun lalu – material yang dilahap (dikonsumsi) setiap orang per tahun hanya 6 ton, manusia pedesaan Eropa tahun 1800an melahap 25 ton, angka itu lantas melesat jauh pada manusia perkotaan tahun 1990an yang memerlukan 100 ton material setiap tahun. Yang menarik untuk dicatat, sepanjang hidupnya manusia Neolithic nyaris tidak menimbun apa pun, sedangkan penerusnya yang hidup pada tahun 1800an dan 1990an berturut-turut diperkirakan menimbun sekitar 80 ton dan 300 ton material sepanjang hidupnya.
Angka itu berlipat dua pada tahun 2017 menjadi lebih dari 700 ton jika mengandaikan rata-rata usia harapan hidup manusia lebih dari 60 tahun. Menurut perhitungan pada tahun 2008, jejak ekologis umat manusia telah mencapai 18,2 miliar global hektare atau sekitar satu setengah kali kemampuan bumi mendukung keberlanjutan kehidupan.
Sayangnya, keberlanjutan sendiri adalah salah satu kata yang paling sulit dipahami. Saking sulitnya untuk dimaknai hingga ada seruan untuk tidak digunakan lagi. Doug King dalam The Conversation (29/8/2013) secara sepaling (extreme) mengusulkan bahwa kata sustainability (keberlanjutan) harus dilarang penggunaanya dalam wacana teknis dan politis.
Menurutnya kata itu telah terkorupsi hingga bukan saja kehilangan makna, tetapi juga cenderung mengaburkan masalah yang sebenarnya harus diatasi. Bisa diduga, hal ini terjadi karena banyaknya kompromi yang harus diambil karena tarik-menarik kepentingan antar pemangku kepentingan. Singkatnya, kata keberlanjutan sudah dibajak, dan menyisakan makna yang kabur, sekadar sesuatu yang berbau lingkungan (an environmental thing). Terlepas dari keruwetan maknanya, hingga kini kata keberlanjutan masih digunakan untuk memberikan ìmuara impianî pembangunan ekonomi – salah satunya dalam rumusan SDGs. Oleh karenanya, kita perlu siasat baru dalam menggunakan kata itu.
Jangan biarkan kata keberlanjutan berhenti sebagai kata benda belaka. Ia harus menjadi ìkata kerjaî alias sustainability at work. Bagaimana mewujudkan itu? Menurut hemat saya, salah satu pilihan jalan tengah untuk mengurai konflik antara pertumbuhan dan keberlanjutan adalah ekonomi sirkular (circular economy, CE). CE menawarkan peluang untuk produk pasca pemakaian didaur ulang (recycled), diperbaiki (repaired) atau di diguna ulang (reused) bukan dibuang; dan limbah suatu proses menjadi asupan (input) proses lainnya.(34)
—Budi Widianarko, guru besar Unika Soegijapranata, anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah.
►Suara Merdeka 20 Juli 2020 hal. 4
https://www.suaramerdeka.com/news/opini/235213-great-reset-dan-keberlanjutan