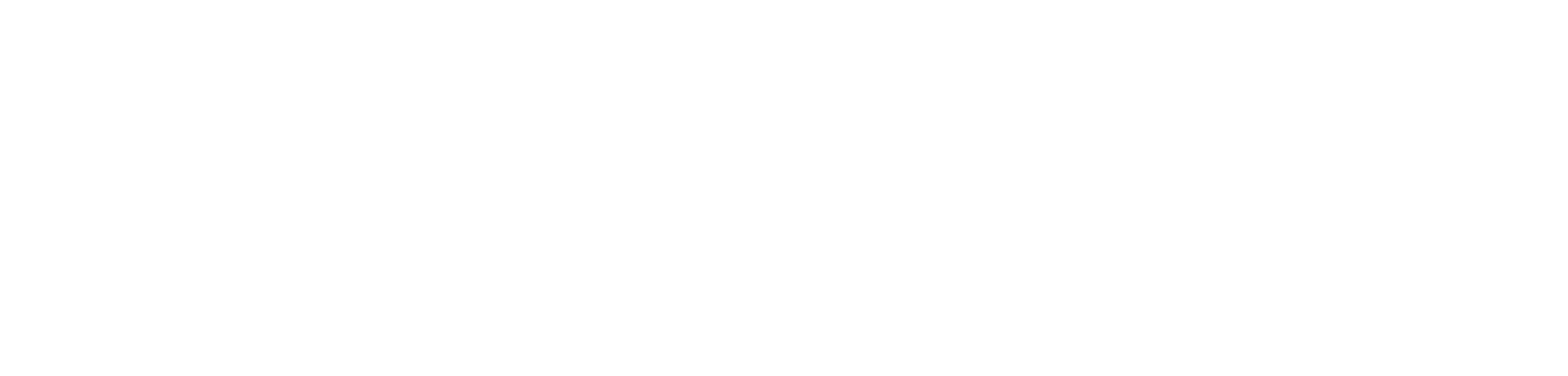Oleh: Aloys Budi Purnomo Pr, Pastor Kepala Campus Ministry; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata Semarang
Ketika Sapardi Djoko Damono, penyair rendah hati dan selalu cool, berpulang ke rahmatullah, 19 Juli 2020; kita semua berduka. Tak hanya dunia sastra dan civitas academica yang berduka, tetapi juga para pecinta hati nurani dan budi pekerti yang saat ini sedang tenggelam dalam arus paradigma post-truth, hoax, dan gosip yang ditaburi kebohongan.
Atas meninggalnya, SDD – begitu sapaan akrab Sapardi Djoko Damono – kita semua berdoa dan percaya bahwa beliau bahagia di surga. Semoga husnul khatimah. Kerendahan hatinya membuahkan kebahagiaan dan kedamaian Surgawi abadi. Rinengga Ingsihing Pangeran (RIP)!
Sebagai rasa hormat dan cinta kepada Sang Penyair, kutuliskan refleksi ini. SDD sudah mengantisipasi kematian itu jauh hari karena kematian memang selalu datang pada waktunya, tak seorang pun bisa meminta atau menolaknya. Dalam bahasa puitiknya, SDD seakan sudah siap menyambut kematian itu. Dia sudah bersajak: “Pada suatu hari nanti/ jasadku tak akan ada lagi/ Tapi dalam bait-bait sajak ini/ Kau tak akan kurelakan sendiri…” (dalam Hujan Bulan Juni, 1991).
Lihat dan rasakan dalam sepenggal bait “Pada Suatu Hari Nanti”, Sang Profesor Sastra sudah berkata: Pada suatu hari nanti/ jasadku tak akan ada lagi… Jasad adalah tubuh kemanusiaan kita. Dan ketika jasadku tak akan ada lagi, itu sama dengan kematian. Namun, SDD sudah mengajarkan melalui puisinya, meski kematian terjadi, ia selalu hadir bersama kita “dalam bait-bait sajak ini/ Kau tak akan kurelakan sendiri.
Yang disajakkannya kini “dihidupinya” dalam keabadian. Itu juga yang disajakkannya pada “Yang Fana Adalah Waktu”. Bagi Penyair kelahiran Solo, 24 Maret 1940 itu, “Yang Fana adalah waktu. Kita abadi:/ Memungut detik demi detik/ Merangkainya seperti bunga/ Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa… (dalam Perahu Kertas, 1983). Di sinilah, puisi menjadi bahasa nurani. Bahkan, panduan dan arahan agar kita hadir sebagai pribadi-pribadi yang ditandai cinta. SDD menjadikan puisi sebagai panduan nurani. Itulah sebabnya, SDD setia berpuisi meski secara intelektual, ia juga seorang akademisi di Universitas Indonesia, alumnus UGM.
Akademisi yang Berpuisi
Sapardi Djoko Damono adalah seorang akademisi yang berpuisi. SDD adalah cendekiawan yang sastrawan. Bahkan, SDD layak disebut pujangga dalam sastra. Sejak remaja SDD sudah bersastra. Sastra adalah jiwa, nurani, hidup dan rumahnya hingga akhir hayatnya.
Meski SDD adalah seorang akademisi, seorang Profesor Doktor, namun dengan rendah hati dicantumkannya “Sastrawan” sebagai pekerjaan di kolom identitasnya. Baginya sastra adalah nafas, nurani, dan jiwanya. Karya-karya kesusastraannya justru menjadi muara bagi seluruh kecendekiawanannya yang melampaui ruang dan waktu. Syair-syairnya sederhana namun berkualitas mendalam karena mengekspresikan perasaan manusiawi yang jujur. Syair-syairnya lugas memancarkan nurani yang tegas namun lembut.
Dalam adagium kuna, Sapardi Djoko Damono selalu fortiter in re, namun suaviter in modo. Bahkan caritas in omnibus. Puisi-puisinya menghadirkan sosok yang teguh dalam prinsip. Namun lembut dalam cara. Bahkan cinta dalam segalanya. Ya, cinta yang sederhana, bahkan tanpa kata! Cintanya menyatu dengan diksi alam semesta.
Kita semua berharap bahwa cintanya kepada alam semesta menginsipirasi kita semua untuk mengembangkan cinta kasih ekologis. Apa itu kasih ekologis? Inilah yang kita cermati pada bagian berikut ini.
Cinta yang Ekologis
Di tengah kompleksitas krisis ekologi yang terjadi karena perilaku manusia yang serakah secara ekonomis, dan ketika seruan solusi-solusi tak mengubah realitas, SDD memberikan alternatif melalui kekayaan filosofis melalui seni dan puisi, kehidupan batin yang jernih dan spiritual yang mengalir bersama semesta. Justru diksi itulah yang terus menyuarakan nuraninya dengan lembut namun tegas plus penuh cinta.
Uniknya, bila kita cermati sajak-sajaknya, bagi saya, sajak-sajak SDD selalu memancarkan cinta yang ekologis. Keterhubungannya dengan siapa saja dibahasakan dengan cinta semesta bersama angin, hujan, api, burung, bunga, dan abu. Cinta itu sederhana. Syair "Aku Ingin" yang musikalisasinya sangat menyentuh mengungkapkan cinta dalam segalanya.
“Aku ingin mencintaimu dengan sederhana/ dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api/ yang menjadikannya abu//Aku ingin mencintaimu dengan sederhana/ dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.” Dan sajak itu begitu saja mengalir mejadi lagu seutuhnya. Sajak dan lagu berpadu dalam musikalisasi yang menjadikan puisi panduan nurani. Cinta bukan tentang hawa nafsu, melainkan pengorbanan!
Cintanya yang ekologis diperdengarkan dalam "Hanya" dengan keintiman spiritual yang istimewa bersama burung, angin, dan doa. “Hanya suara burung yang kau dengar/ Dan tak pernah kulihat burung itu/ Tapi tahu burung itu ada di sana/ Hanya desir angin yang kurasa/ Dan tak pernah kulihat angin itu/ Tapi percaya angin itu di sekitarmu/ Hanya doaku yang bergetar malam ini/ Dan tak pernah kaulihat siapa aku/ Tapi yakin aku ada dalam dirimu.”
Cinta yang ekologis pun tampak dalam "Hujan Bulan Juni"-nya. Baginya "tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni/ Dirahasiakannya rintik rindunya/ kepada pohon berbunga itu/ tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni…. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni/ dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu.” Seiring kepergiannya, hujan tak lagi jatuh di bulan Juni, melainkan menderaskan duka bulan Juli. Namun, mari kita ingat pesannya: Pada suatu hari nanti/ jasadku tak akan ada lagi/ Tapi dalam bait-bait sajak ini/ Kau tak akan kurelakan sendiri.
Di sinilah, puisi sebagai panduan nurani menjadi warisannya sebab kita selalu ada bersama sesama dan semesta. Jadi mari saling mencintai, meski dengan cara sederhana. Jauhkan setiap hujat, hoax, gibah, dan gosip dari diri kita sehingga kita tetap rukun sebagai saudara sebangsa!
► https://investor.id/opinion/menjadikan-puisi-panduan-nurani