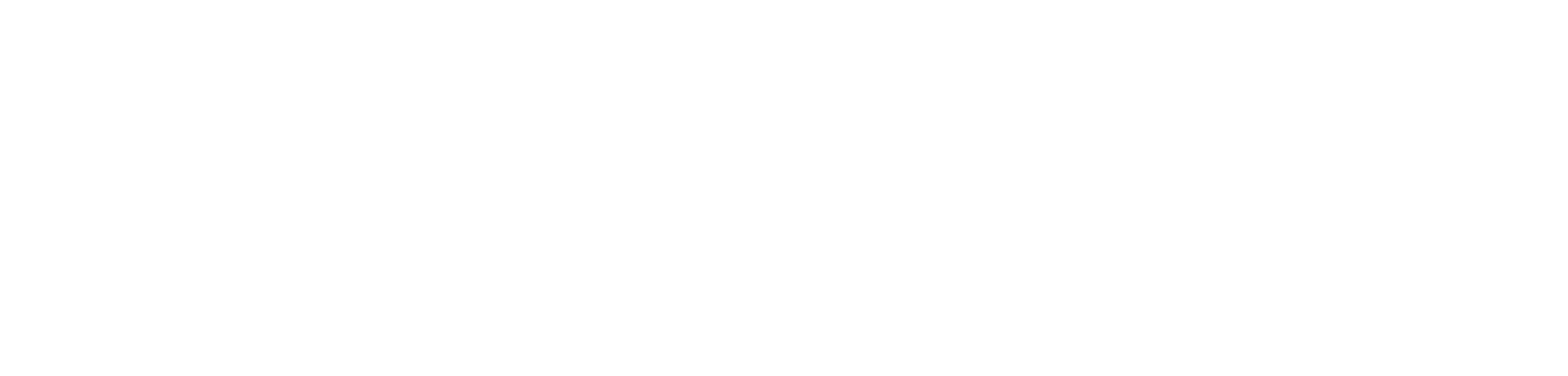Pandemi Covid 19 masuk dalam kategori bencana non alam. Pandemi tidak sekadar soal penanggulangan, tetapi bagaimana tuntutun kebijakan sesudahnya yang masuk dalam darurat demokrasi. Pandangan itu disampaipaikan Pengamat Politik dari Unika Soegijapranata, Drs Andreas Pandiangan MSi saat menjadi salahsatu narasumber di acara Ngobrol Virtual yang diselenggarakan Suara Merdeka secara virtual, kemarin.
“Kita pahami situasi ini tidak sehadar urusan kesehatan penanggulangun Covid-19, tetapi tuntutan kebijakan sesudah itu sebenarnya masuk dalm darurat demokrasi juga,” kata Andreas, sapaan akrabnya.
Selain Andreas Pandiangan, sejumlah narasumber lain turut hadir, seperti Petieliti Kebahasaan, Penulis Buku Saling Silang Indonesia-Eropa Joss Wibisono; Prosuder Film, Aktivis Kesetaraan dan Keberagaman Gender Tunggal Pawestri; dan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo.
Andreas melihat ada satu keunikan terkait pandemi Covid-19, yaitu pada 31 Maret 2021, pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia masuk dalam darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19. Kemudian tidak sampai dua pekan berikutnya, yaitu 13 April 2020 pemerintah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai bencana non-alam.
“Buktinya pada 31 Maret 2020 saat masih dinyatakan darurat kesehatan dikeluarkan Perpu No 1 Tahun 2020,” katanya.
Menurutnya, selain persoalan soal kebijakan ekonomi dan moneter, di situ ada persoalan khusus tentang bagaimana kepala daerah diberi wewenang berupa kekuasaan untuk membuat kebijakan yang oleh pemerintah disebut sebagai refocusing anggaran.
Mungkin bagi masyarakat waktu itu tidak disadari, bahwa hal itu tidak hanya penanggulangan kesehatan. Tetapi pada tataran pemerintah daerah sebetulnya terjadi kedaruratan demokrasi.
“Karena kebijakan pembangunan yang cerminnya pada anggaran sudah tidak melalui proses perencanaan yang mau tidak mau memerlukan persetujuan DPRD,” terangnya.
Pada tataran itu, Andreas melihat terjadi kedaruratan demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, adanya Perpu No 1 Tahun 2020 tersebut yang beberapa bulan kemudian disahkan menjadi undang-undang ada semacam kedaruratan demokrasi.
“Jadi bukan hanya darurat bencana lokal kesehatan, melainkan juga darurat demokrasi yang berlangsung hingga sekarang, ujarnya.
Ia mencontohkan bagaimana seorang kepala daerah menyelenggarakan pemerintah di daerah di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, melihat kondisi Indonesia tidak cukup dilihat dari perilaku kebijakan di Jakarta, tetapi juga dilihat di pemerintah daerah.
“Mereka diberi keleluasaan untuk mengambil kebijakan. Salah satunya bermuara pada pengalihan lokasi anggaran yang tidak sepenuhnya harus melalui DPRD,” ujarnya.
Berlanjut
Adapun di DPRD, kata dia, hanya bentuk penjelasan. Ini belurn melihat pada persoalan apakah transparan atau tidak, tetapi prosesnya. Padahal di APBD ada politik anggaran yang menjadi cerminan bagaimana salah satu demokrasi di daerah itu berjalan apa tidak.
“Soal anggaran dibicarakan, didiskusikan antara kepala daerah dan DPRD. Kita, punya 500 an lebih provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” terangnya.
Ia melanjutkan, kedaruratan demokrasi berlanjut pada pelaksanaan Pilkada kemarin. Ada 270 daerah atau hampir setengah daerah yang melaksanakan Pilkada.
Menurutnya, memilih pemimpin dalam kondisi darurat kesehatan sempat menuai banyak protes. Karena masyarakat tidak cukup waktu dan ruang untuk bertemu dengan calon pemilihnya. “Mungkin bagi penyelenggara itu sebagai keberhasilan, karena mampu menyelenggarakan pemilu di tengah Covid-19 dan kekhawatiran terjadinya claster Covid-19 Pilkada tidak terjadi,” ujarnya.
Tetapi proses Pilkadanya sendiri yang berlangsung hampir di setengah dari wilayah Indonesia ini itu tidak berjalan normal. Menurutnya, tidak ada kesempatan bagi pemilih mendengarkan sejumlah program dari calon yang akan dipilih. Masyarakat tidak cukup waktu untuk mencermati, kemudian memilih karena kondisi Covid-19.
►Suara Merdeka 3 Oktober 2021 hal. 12