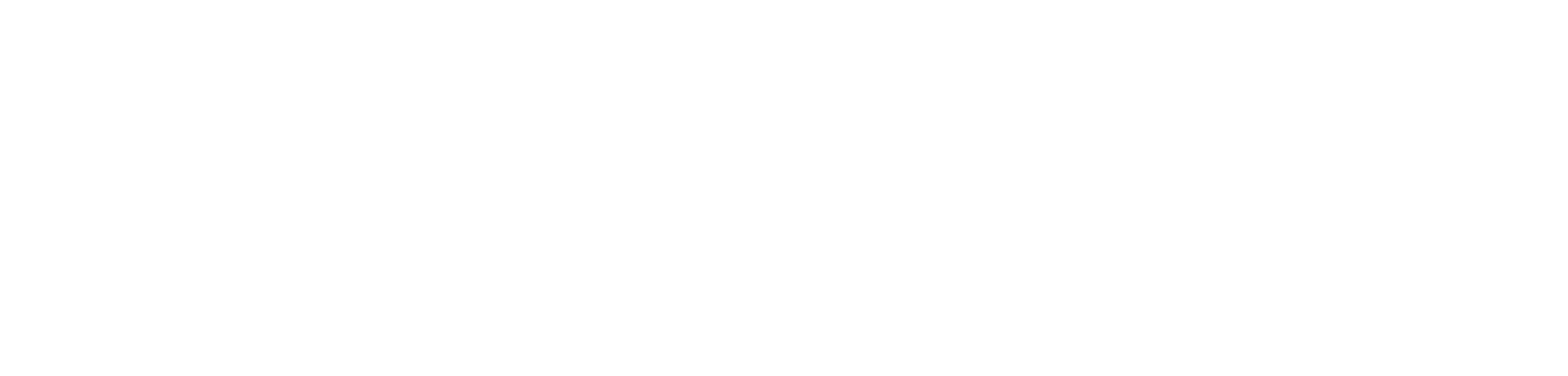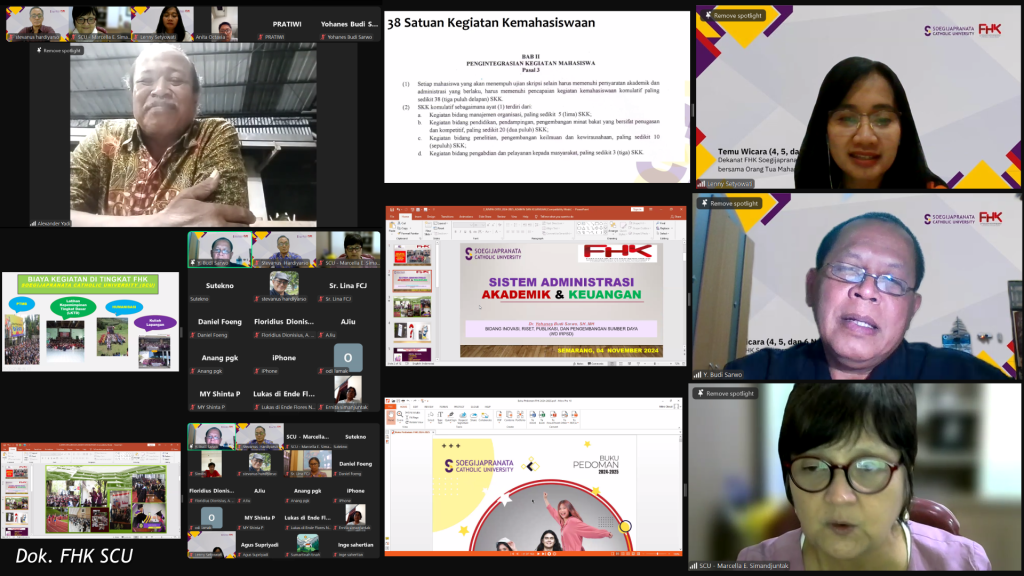Oleh Aloys Budi Purnomo Pr, Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata
Memasuki Desember, iklim normal di Indonesia akan bertaburan hujan, meski kini, akibat krisis iklim, dua musim di negeri ini tak lagi normal. Desember, orang Jawa bilang sebagai jarwa dhosok (kerata basa) singkatan dari “gedhe-gedhene sumber”. Sumber mata air mengalir melimpah. Bahkan sampai Januari, yang jarwa dhosok-nya “hujan sehari-hari”, musim penghujan masih bisa dinikmati. Baru kemudian di bulan Maret, jarwa dhosok dari mak ret, hujannya cuma sebentar dan di bulan April mulai mipril sebagai jarwa dhosok.
Namun, itu dulu. Sekarang tampaknya semuanya serba unpredictable. Penyebab utamanya adalah terjadinya perubahan iklim global.Dampaknya krisis iklim, bahkan krisis lingkungan, dan krisis ekologi.
Krisis ekologi
Para ahli memverifikasi krisis ekologi sedikitnya tampak dalam beragam gejala, sedikitnya tujuh (Fransiskus, 2015; Keraf, 2010). Pertama, masalah polusi dan perubahan iklim. Kedua, krisis air yang merupakan kebutuhan dasar semua makhluk. Ketiga, punahnya keanekaragaman hayati. Keempat, kemerosotan sosialkualitas hidup manusia. Kelima, ketimpangan global lingkungan dengan dampak terburuk bagi yang paling lemah dan miskin.
Keenam, lemahnya tanggapan-tanggapan berbagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab telah memperparah krisis ekologi. Contoh paling nyata adalah lemahnya respons politik internasional atas perubahan iklim dan gagalnya KTT global tentang lingkungan hidup November 2021 lalu mencapai kesepakatan tegas mengurangi emisi. Itu akibat pembenaran sistem global yang mementingkan spekulasi dan kejar target laba finansial.
Ketujuh, keragaman pendapat dan argumentasi dalam menyikapi krisis ekologi. Pengutamaan pada solusi teknis telah mengabaikan pertimbangan etis. Alih-alih mengatasi krisis justru menghalalkan segala cara dengan mengabaikan prinsip moral.
Kejujuran ekologis
Dalam keragaman pendapat itu, haruslah diutamakan dialog yang jujur. Kejujuran ekologis itulah yang saat ini hilang di antara kita, terutama di kalangan para pemimpin politik dan ekonomi kita (Dawn M. Nothwehr, 2020).
Lawan kejujuran ekologis adalah ketidakjujuran anti-ekologis. Menurut John F. Haught (2020) alasannya adalah materialisme yang secara inheren bertentangan dengan semua gagasan tentang alam semesta yang memiliki tujuan intrinksiknya. Pierre Teilhard de Chardin,pemikir agama abad kedua puluh yang canggih secara ilmiah telah mengingatkan kita dengan kerangka kerja yang lebih dapat dipahami untuk memahami hubungan sains dengan agama, dan dengan implikasi ekologi dengan teologi berbasis kejujuran ekologis.
Teilhard menegaskan bahwa jika Tuhan mencintai dunia, kita juga harus demikian. Sebaliknya, jika alam semesta fisik adalah “segalanya”, maka alam tidak akan pernah bisa mengklaim cinta dan rasa hormat kita sepenuhnya. Masalahnya adalah kita hanya dapat mencintai sepenuhnya apa yang menjadi bagian dari keabadian, toleransi materialisme yang angkuh terhadap prospek perjalanan terakhir alam menuju ketiadaan. Jika seluruh alam pada akhirnya ditakdirkan untuk ketiadaan, seperti yang diklaim oleh para pesimis kosmik, kepercayaan seperti itu tidak dapat membenarkan moralitas ekologi antargenerasi yang kuat.
Akibatnya, alam ciptaan melulu dipandang materialistis ekonomis lantas lahirlah perilaku eksploitatif terhadap alam semesta. Alam dipandang sekadar benda mati yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan ekonomis.
Romantisme Hijau
Di sinilah pentingnya romantisme hijau. Jangan keliru, romantisme hijau bukan ilusi imajinatif tenang teduh, melainkan satu perjuangan dalam kelembutan kasih memaham dan memperlakukan Bumi dan seisinya. JonathanBate (1993) berpendapat, misalnya, bahwa jika seseorang menghistoriskan dari sudut pandang ekologis, rasa hormat terhadap Ibu Pertiwi akan mengalir dari kedalaman jiwa manusia kasih sayang terhadap alam ciptaan. Romantisisme hijau bahkan menginspirasi gerakan green politicianskontemporer melawan efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon, perusakan hutan hujan tropis, polusi laut, dan segala bentuk degradasi lingkungan karena ketamakan dan kerakusan!
Romantisme hijau amat penting dalam menumbuhkan apresiasi terhadap alam. Namun, seperti yang terlihat dalam tulisan lingkungan populer, alih-alih menjauh dari pemikiran ilmiah, rasa hormat terhadap alam romantisme hijau justru ama berbasis pada logika ilmiah (Oliver George, 2017). Contoh paling legendaris penyinergi romantisme hijau dan logika keilmuwan adalah Rachel Carson, dalam buku revolusionernya, Silent Spring (1962), yang secara efektif meluncurkan gerakan lingkungan modern.
Carson membuka bukunya dengan“Fable of Tomorrow” yang secara romantis menggambarkan kota yang damai, mekar dengan kehidupan. Namun, tiba-tiba, “mantra jahat” menguasai kota dan dalam kehancurannya menimbulkan “bayangan kematian”. Hewan-hewan yang sebelumnya sehat terbaring terserang penyakit, dan bunga-bunga indah kehilangan warna cerahnya, berfungsi sebagai peringatan akan bahaya bahan kimia buatan manusia. Dengan refleksinya, Carson telah menarik emosi pembaca, namun penjelasan ilmiah tentang bagaimana organisme saling berhubungan, terutama melalui rantai makanan, berfungsi sebagai dasar untuk memahami mengapa kelestarian lingkungan dan keutuhan ciptaan harus diperjuangkan!Meski romantis, ia tetaplah rasional!
►https://jateng.tribunnews.com/2021/11/30/opini-aloys-budi-purnomo-pr-rasionalitas-romantisme-hijau?page=all.
Tribun Jateng 30 November 2021 hal. 2