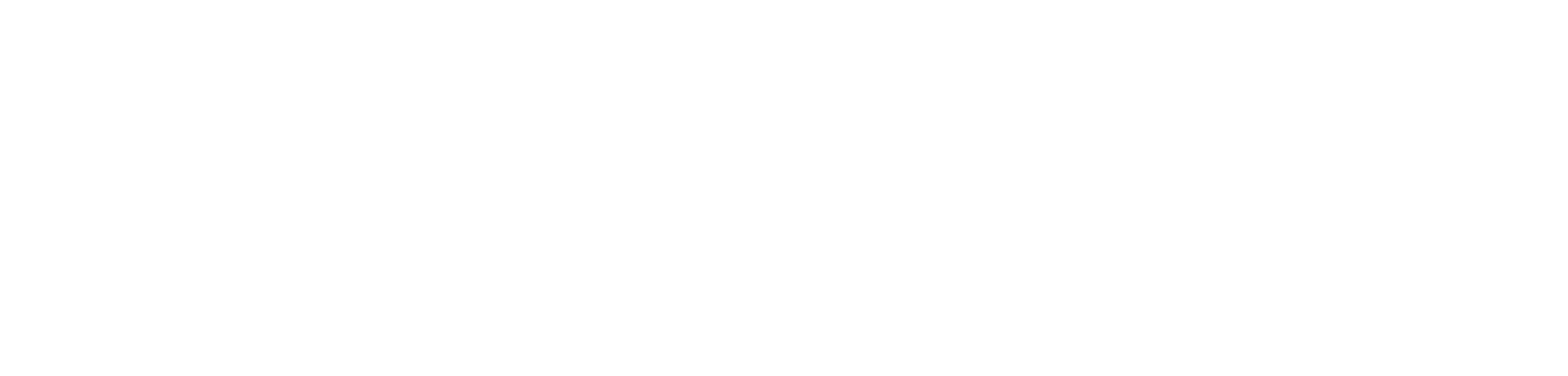Konsorsium Ground Up sedang melakukan penelitian di Semarang dengan yang mengusung tema “Analisis Praktis Tata Kelola Air Tanah Menuju Manajemen Air Perkotaan Terpadu di Semarang”, sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengetes, dan mengevaluasi kemungkinan praktis untuk perpaduan aliran air tanah dan aliran air permukaan yang lebih berkeadilan dan lestari.
Ground Up merypakan konsorsium yang terdiri dari Universitas Belanda (University of Amsterdam dan IHE-Delft Institute for Water Education), Universitas di Indonesia (Universitas Gadjah Mada/UGM, Universitas Diponegoro, dan Unika Soegijapranata, Semarang), dan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Amarta Institute for Water Literacy dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air/KRuHA).
Riset ini dibiayai oleh Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW, Lembaga Belanda untuk Riset dan Pengetahuan) dengan Ristekdikti (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Indonesia).
Anggota Konsorsium Ground Up dari Amrta Institute for Water Literacy Nila Ardhianie mengatakan Semarang adalah wilayah dengan tantangan pengelolaan air yang kompleks, sehingga penting untuk mengintegrasikan berbagai aspek dalam merancang tata kelola air yang efektif.
Menurutnya, karena kompleksnya masalah tata kelola air di Semarang, Ground Up mencoba mendekatinya dengan cara menyusun anggota konsorsium dengan berbagai latar belakang pendidikan, misalnya dari latar belakang geologi, ekonomi, arsitek, politik, teknik industri, manajemen lingkungan, dan geografi manusia (human geography).
“Konsorsium Ground Up berdiri pada 2019 dan akan mengadakan penelitian di Semarang hingga 2022. Mereka mengundang wartawan untuk berbagi sebagian hasil awal penelitian mereka,” ujar Nila panggilan akrab Nila Ardhianie saat mengawali diskusi mengenai tata kelola air di Semarang, Jum’at (31/1).
Ketua Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM Amalinda Savirani yang merupakan koordinator konsorsium Ground Up untuk Indonesia, menuturkan secara kebahasaan “Ground Up” berarti “dari bawah ke atas”.
“Artinya Ground Up ingin memahami tata kelola air di Semarang secara terpadu, dari bawah ke atas,” tuturnya.
Menurutnya, permasalahan air di Semarang sudah sangat kritis. Misalnya, dari akun media sosial Walikota, terlihat betapa banyak isu soal air didisukusikan oleh warga net. Bahkan permasalahan krisis air, misalnya air minum, di Kota Seperti Semarang bukan karena tidak ada air. Tapi kenyataannya banyak warga yang kekurangan air.
Dari 1900 sampai 2000-an, lanjutnya, ekstraksi air tanah di Semarang meningkat sangat ekstrim. Dari sekitar 0,4 juta meter kubik per tahun pada 1900, menjadi sekitar 38 juta meter kubik per tahun pada 2000-an.
Kondisi itu, dia menambahkan mengakibatkan terjadinya ekstraksi air tanah ini, salah satu dampaknya adalah terjadinya amblesan tanah di Kota Semarang, terutama di daerah Semarang Utara.
Amblesan tanah di beberapa bagian Semarang Utara-Timur dengan kecepatan 10 cm per tahun. Sedangkan di beberapa tempat, misalnya di Tambak Lorok, warga harus menaikkan lantai rumahnya. Bahkan ada yang sampai setiap 5 tahun sekali warga yang harus menaikkan lantai rumahnya.
Selain amblesan tanah itu, tutur Amalinda, masalah lain adalah abrasi. Sejak 1972 hingga 2019 berdasarkan data dari citra satelit, di daerah Semarang-Demak sudah terabrasi seluas 4.274 hektare tanah.
Dia mengatakan Ground Up mendekati permasalahan ini dengan cara pandang sosio-teknis, artinya dengan juga mempertimbangan peran warga dalam solusi-solusi yang akan diambil.
Kepala Jurusan Tata Kelola Air (Water Governance) IHE-Delft Intitute for Water Education Michelle Kooy menyebutkan kasus yang dihadapi oleh Semarang dihadapi juga oleh banyak kota di dunia. Misalnya, masalah amblesan tanah, ekstraksi air tanah, dan juga banjir, ada di banyak kota yang dekat dengan laut, misalnya di Filipina, Vietnam, Afrika, Amerika Latin. #
“Yang kami kaji adalah bagaimana kita semua merespon krisis ekologi ini. Agar tanggapan atau respon kita terhadap krisis ekologi ini bersifat partisipatif dan terbuka. Misalnya, dalam kasus Told an Tanggul Laut Semarang-Demak, pertanyaan yang muncul dari kami misalnya, siapa yang akan dilindungi oleh proyek infrastruktur itu?,” ujarnya.
Siti Rukayah dari Jurusan Arsitektur Undip yang merupakan anggota konsorsium Ground Up mengatakan dalam penelitiannya menyebutkan mencermati cepatnya penurunan tanah. Ilmu arsitektur bisa melakukan pengukuran di gedung-gedung yang ambles.
“Dalam penelitian saya tahap pertama, sudah muncul hasil sementara. Misalnya, bangunan tua bisa dipakai oleh masyarakat untuk mengenali/mengidentifaksi terjadinya penurunan tanah,” tuturnya.
Wijanto Hadipuro dari Unika Soegijapranata menyampaikan ikut terlibat dalam Ground Up karena tertarik dengan perspektif riset Ground Up yang tidak teknikal.
Dalam pandangan Wijanto, yang menarik dari Ground Up adalah pendekatan “practice-based”. Yaitu, kira-kira masyarakat Kota Semarang memiliki banyak pengetahuan awal.
Masyarakat, lanjutnya, sudah mengetahui adanya pembangunan-pembangunan di bagian utara Semarang di masa lalu mengubah arus laut dan menyebabkan abrasi di beberapa tempat. Jadi jangan sampai pembangunan Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak menjadi memperparah abrasi di tempat lain.
Wijanto melihat pendekatan practice-based ini memiliki sifat kerendah-hatian dari akademisi. Akademisi belajar melalui riset dan buku. Sementara warga yang tinggal di daerah-daerah tertentu belajar dari kehidupan. Akademisi dengan pendekatan practice-based ini memiliki kesempatan untuk belajar dari masyarakat.
Wijanto juga menyampaikan kekhawatirannya. Bahkan menurutnya, sudah muncul di Jakarta dengan apa yang dia sebut sebagai “disaster capitalism,” dimana bencana yang disebabkan oleh proyek-proyek pembangunan dicoba diatasi dengan proyek pembangunan yang lain.
Jadi, tutur Wijanto, jangan sampai, pengelolaan lingkungan yang buruk menjadi peluang untuk munculnya kesempatan untuk akumulasi kapital bagi sekelompok orang.
Koordinator KruHA Muhammad Reza Sahib menuturkan dalam banyak proyek infrastruktur yang menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan air, warga yang senantiasa jadi korban proyek skala besar perlu saluran aspirasi guna menghindari situsai yang memperburuk kualitas hidup, juga konflik sosial.