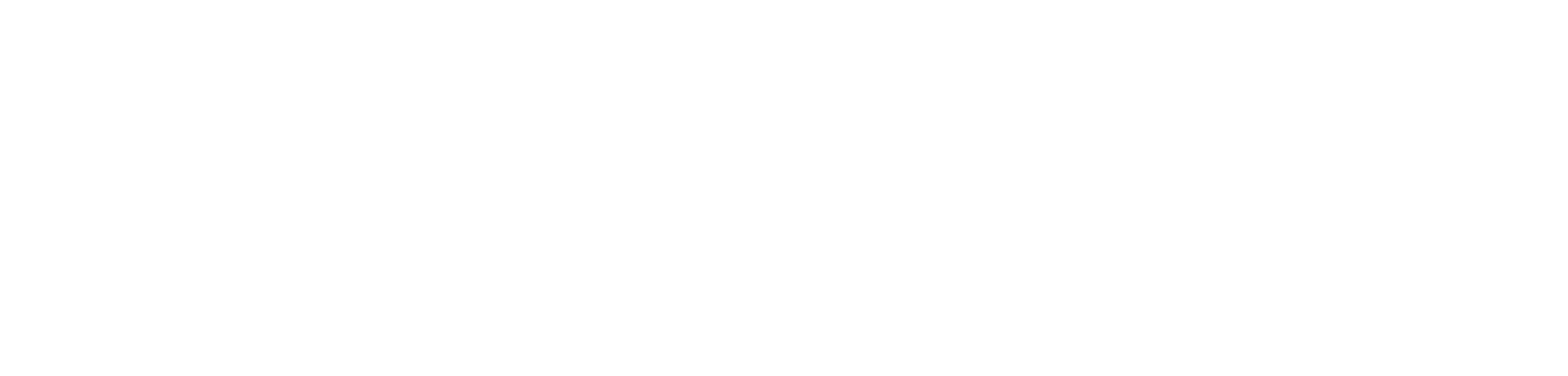Oleh Ferdinand Hindiarto, Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
Namun setelah berjalan hampir dua tahun berbagai aktivitas itu dilakukan secara daring, kita sepertinya terjebak di zona nyaman yang baru. Banyak orang mulai enggan dan berat untuk bekerja secara langsung atau sebagian yang lain lagi enggan untuk belajar dan eng-gan beribadah secara langsung.
SERING kita mendengar ungkapan, “Kita harus berani keluar dari zona nyaman.” Namun sebaliknya, ada ungkapan lain, “Bukankah setiap orang justru mencari dan memperjuangkan kenyamanan, mengapa harus keluar dari sana?”
Dialog ungkapan-ungkapan itu menyerupai sebuah paradoks, namun sebenarnya lebih tepat disebut sebagai sebuah siklus. Tentu saja setiap orang atau organisasi akan berjuang untuk mencapai situasi kenyamanan dan menikmatinya.
Namun jika situasi itu berlangsung dalam waktu yang lama, banyak hal yang dilakukan akan cenderung menjadi sebuah rutinitas. Dan jika hal itu terjadi maka ruang-ruang kreativitas dan inovasi menjadi sangat sempit. Pengembangan pribadi ataupun organisasi juga akan cenderung stagnan. Dalam bahasa Jawa sering diungkapkan, “Ngene wae ya wis cukup kok.”
Sebagai sebuah siklus, maka baik individu maupun organisasi perlu memiliki mekanisme agar tidak terjebak dalam zona nyaman yang terlalu lama. Berputar dan kembali. Artinya, ketika individu berjuang dan mendapatkan kenyamanan, seharusnya akan kembali muncul kecemasan dan kegelisahan untuk menemukan sesuatu yang baru dan lebih baik.
Dalam kurun hampir dua tahun terakhir, kita mendapat pelajaran berharga akibat pandemi Covid-19. Pada awal pandemi, banyak orang yang merasa cemas ketika harus melakukan berbagai aktivitas secara online. Belajar, bekerja, beraktivitas sosial, dan beribadah harus dilakukan secara online. Saat itu banyak orang merasakan ada sesuatu yang hilang. Tidak mudah pula bagi sebagian orang untuk beradaptasi dengan situasi baru tersebut akibat terlalu lama berada di zona nyaman yang sudah dirasakan sebelumnya.
Namun setelah berjalan hampir dua tahun berbagai aktivitas. itu dilakukan secara daring, kita sepertinya terjebak di zona nyaman yang baru.
Banyak orang mulai enggan dan berat untuk bekerja secara langsung atau sebagian yang lain lagi enggan untuk belajar dan enggan beribadah secara langsung. Sudah merasa nyaman melakukan berbagai hal secara virtual. Perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan secara virtual seolah sudah dianggap cukup meski secara hakiki sebenarnya banyak yang “hilang” dari perjumpaan semacam itu.
Sebagai contoh dalam konteks dunia pendidikan. Sejatinya pendidikan tidak sekadar mentransfer pengetahuan dari guru/dosen kepada siswa/mahasiswa.
Pendidikan tidak hanya berdimensi pada pengetahuan saja. Namun harusnya menjangkau dimensi penanaman nilai-nilai, pembangunan karakter. pembentukan kompetensi-kompotensi sosial, yang jika dilakukan secara virtual tentu akan sulit terjadi.
Misalnya menanamkan nilai empati, dapat dilatih saat para siswa bersedia mendengarkan siswa lain berbicara atau berpendapat, termasuk melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Dalam pembelajaran online semua itu tidak dapat dilakukan dengan baik karena guru/dosen tentu tidak dapat mengontrol perilaku siswa/mahasiswa lain saat ada temannya sedang mengemukakan pendapat.
Namun rupaanya saat ini bukan hal yang mudah untuk mengajak para siswa/mahasiswa atau bahkan guru/dosen untuk kembali pada pembelajaran tatap muka (PTM). Berbagai alasan pun dikemukakan. Misalnya, ada kekhawatiran pembelajaran tatap muka dapat menjadi klaster baru penularan Covid-19 dengan segala variannya.
Ekspresi Keengganan
Namun sesungguhnya kekhawatiran itu muncul sebagai sebuah ekspresi keengganan untuk keluar dari zona nyaman. Hampir dua tahun menikmati pembelajaran daring telah membuat mereka merasakan kenyamanan.
Akibatnya, mereka pun merasa tidak perlu pergi ke sekolah, tidak perlu uang transpor, tidak perlu bayar biaya kos, belajar-mengajar dapat dilakukan sambil mengerjakan hal lain, serta kenyamanan-kenyamanan lain yang memperkuat zona nyaman itu. Soal efektif atau tidak, seolah kalah oleh kenyamanan yang mereka rasakan. Soal out-comes mau seperti apa, sepertinya bukan hal yang penting lagi.
Alasdair White. penulis buku From Comfort Zone to Performance Management (2009) menyebut zona nyaman sebagai a behavioural state within which a person operates in an anxiety-neutral condition, using a limited set of behaviours to deliver a steady level of performance, usually without a sense of risk. Dalam zona nyaman individu berada dalam kondisi normal tanpa adanya kecemasan, individu hanya menggunakan separangkat perilaku terbatas yang dimilikinya untuk mencapai level performa tertentu dan cenderung menghindari risiko. Jelas sekali bahwa zona nyaman akan menjadikan individu-individu enggan untuk melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu dengan usaha yang lebih keras.
Zona nyaman memang menyerupai sebuah siklus. Dan saat siklus itu berjalan dalam waktu yang panjang akan membuat manusia enggan melakukan perubahan. Pandemi Covid-19 ini telah memberikan pelajaran berharga bagi manusia tentang beratnya keluar dari zona nyaman.
Kita boleh menikmati zona nyaman sebagai cara untuk membangun self esteem yang lebih kuat. Namun di sisi lain, jika perlu harus dihadirkan kecemasan atau kekhawatiran baru, atau disebut dengan fear zone, dengan mengungkapkan pertanyaan: Apakah betul sudah cukup? Apakah betul hasilnya sudah maksimal? Apakah tidak ada cara lain?
Beberapa ahli psikologi, seperti David McClelland menyatakan bahwa dalam batas tertentu kecemasan justru akan memicu meningkatnya performa. Maka panduan antara kekuatan self esteem yang diperoleh dari zona nyaman dan kekhawatiran dari fear zone seharusnya menjadi energi untuk berani menemukan cara-cara baru dalam berpikir, bersikap, dan bertindak serta beradaptasi dengan berbagai perubahan yang akan terjadi. Itulah cara terbaik untuk memperpendek siklus zona nyaman.
►Suara Merdeka 18 Desember 2021 hal. 4