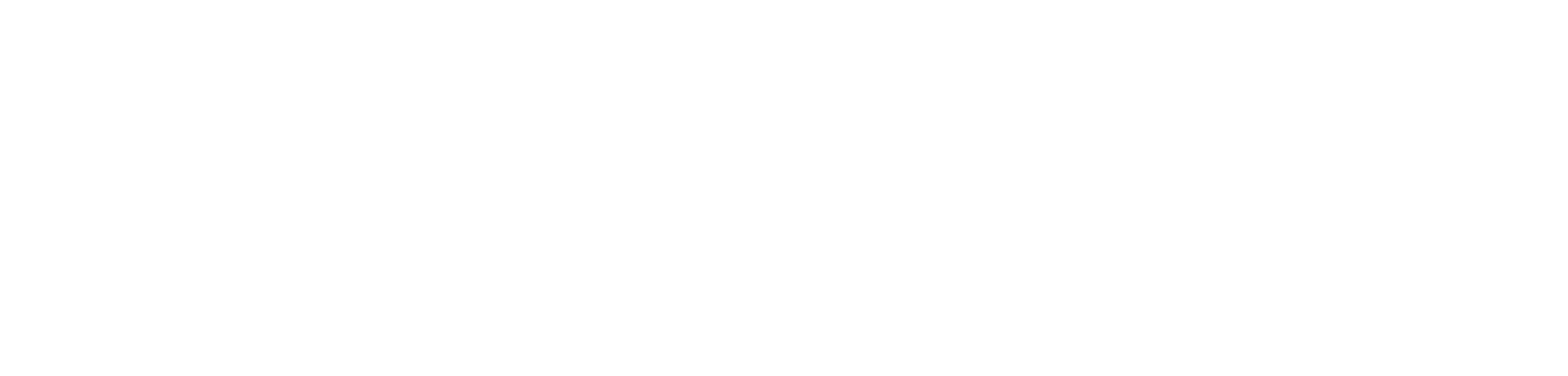Oleh: Budi Widianarko
“Esensi keunikan manusia mewujud dalam proses pemahaman tentang pribadi melalui liyan”
SAAT keluar dari gedung First Squaredi Kota Taichung, Taiwan, pertengahan Maret lalu, saya tak bisa mengalihkan pandangan dari sebuah tenda putih besar dengan semacam bazar buku di bawahnya. Begitu mendekat, saya menemukan deretan buku berbagai bahasa Asia Tenggara, seperti Indonesia, Tagalog, Thai, dan Vietnam.
Buku berbahasa Indonesia saya temukan beragam, dari sebuah novel Pramudya Ananta Toer, buku pengembangan diri, hingga buku tentang hama penyakit tanaman. Didorong rasa penasaran, saya masuk ke tenda dan menyaksikan beberapa anak muda sedang membaca buku. Sebuah perpustakaan hadir di tengah keramaian salah satu jantung Kota Taichung.
Saya mencoba berbincang dengan pemrakarsanya, Annie, seorang perempuan Taiwan yang terlihat masih sangat muda. Dia menjelaskan, kegiatan yang saya saksikan ini pelayanan perpustakaan untuk pekerja migran di Taichung. Kegiatan itu diprakarsai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama 1095 Culture Studio yang didirikan oleh Annie bersama tiga temannya. Dari perbincangan akhirnya saya tahu, Annie adalah lulusan S-1 Sejarah dan S-2 Warisan Budaya dari salah satu Universitas negeri (nasional) ternama di Taiwan.
Di bawah tenda itu saya juga dipertemukan dengan Ida, perempuan muda asal Malang, sukarelawan di LSM tersebut yang sebenarnya adalah pekerja migran. Dengan ramah Ida menyapa teman sesama pekerja migran dalam logat Malang yang kental. "Ayo maca, aja mung mlaku-mlaku," sapanya.
Begitu menemukan buku yang cocok, pengunjung pun duduk di bagian tengah tenda dan mulai Membaca.Tepat di seberangtenda ada semacam undhak-undahkan yang dipadati pekerja migran dari berbagai negara, duduk bercengkerama di tengah keriuhan "Asia Tenggara Kecil" Taichung itu.
Dari Ida saya tabu, ada juga organisasi sosial lain di Taichung yang menyelenggarakan kursus bahasa Mandarin gratis bagi pekerja migran Indonesia di ASEAN Square —nama baru bagi First Square. Pengajarnya Nurul, perempuan warga Malaysia, yang pernah kuliah dan kini bekerja di Taiwan.
Yang menarik, meski prodeo, peserta diharuskan menyerahkan uang jaminan (deposit) sebesar 2000 dolar Taiwan (NTD) atau setara dengan satu juta rupiah dan uang itu tidak akan dikembalikan jika peserta mangkir lebih dari dua kali.
Memang kursus ini tidak hanya menggembleng literasi bahasa Mandarin, tetapi juga merawat motivasi dan kesungguhan belajar para peserta.
Memberdayakan Liyan
Yang menarik untuk dicermati adalah kehadiran sukarelawan Annie, Ida, dan Nurul dalam memberikan pelayanan bagi pekerja migran. Bagaimana sikap altruis itu lahir dan membesar serta mewujud menjadi kegiatan pemberdayaan yang nyata merupakan teka-teki yang sangat menarik.
Tiga perempuan, tiga kebangsaan —Taiwan, Indonesia, Malaysia— mencurahkan daya dan tenaga untuk memberdayakan orang lain. Untuk kasus Annie, mungkin kita bisa mengatakan dia memang memilih profesi sebagai aktivis LSM. Sebenarnya, perempuan muda ini secara penampilan, kecerdasan, dan pendidikan sangat punya peluang berkarier di korporasi, tetapi entah kenapa dia memilih karya sosial.
Dan mimik bicara dan bahasa tubuh saat menuturkan prakarsanya, saya menangkap getaran empati yang kuat. Keberpihakannya kepada pekerja migran —yang datang ke negaranya—benar-benar datang dari hati.
Ida tidak kalah unik. Alih-alih menikmati akhir pekan untuk melepas sejenak kepenatan kerja, dia justru menghabiskan waktu "berharga" itu untuk terlibat dalam pemberdayaan sesama pekerja migran.
Begitu pula Nurul. Mengapa pula perempuan Malaysia ini merelakan akhir pekannya untuk memintarkan para pekerja migran asal Indonesia? Tampaknya, persaudaraan serumpun saja tidak cukup kuat untuk menjelaskan kesungguhannya menjalani pekerjaan yang nyaris tidak berbayar itu. Semua itu seperti misteri.
Larisa Korobeynikova (2015), peneliti di Universitas Tomsk, Rusia, punya rumusan yang indah tentang teka-teki manusia ini. "Toleransi bisa terjadi dalam lingkup nilai-nilai budaya yang tidak terbatas pada makna, tetapi juga tujuan, di mana keberpihakan kepada orang lain bukan sekadar subjek legitimasi, melainkan juga nilai. Lebih lanjut, dia menulis, "Esensi keunikan manusia mewujud dalam proses, pemahaman tentang pribadi melalui liyan. Tidak sekadar mengenali liyan, tetapi menerapkan toleransi terhadap liyan mungkin merupakan prasyarat bagi pribadi dalam menetapkan tapak dan rasa mengada di dunia multikultural."
Mungkin dorongan empati kepada liyan inilah yang menjelaskan mengapa ketiga perempuan muda di Taichung itu melibatkan diri dengan sepenuh hati dalam kancah pemberdayaan para pekerja migran.
—Budi Widianarko | dosen Unika Soegijapranata, guru besar tamu di P tovidenee University; Taiwan.
►Suara Merdeka 2 April 2018, hal. 4, http://www.suaramerdeka.com