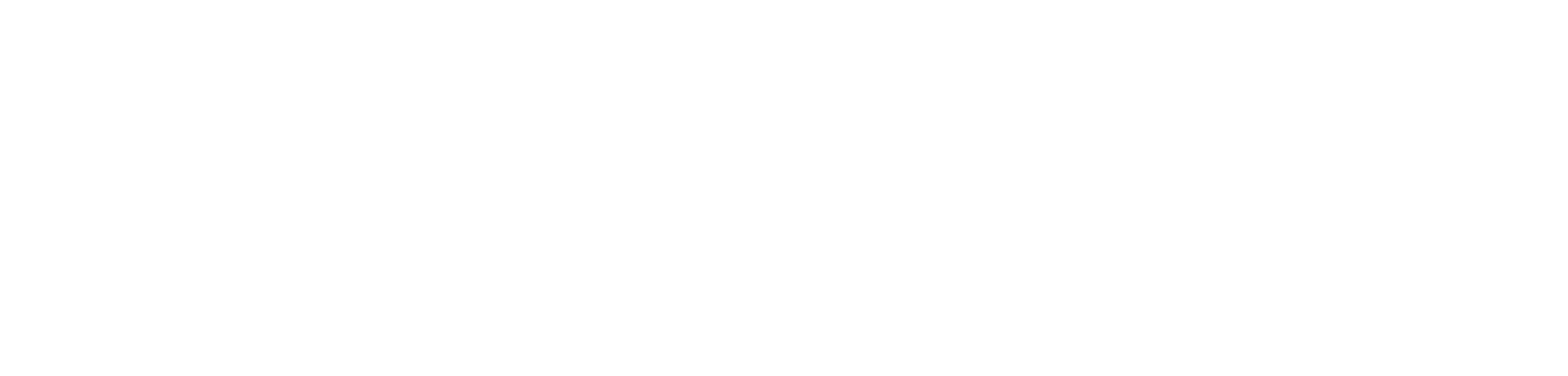Oleh Dr Ferdinand Hindiarto, dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang.
"Jika program ini akan diimplementasikan, sebaiknya perguruan tinggi mengolahnya kembali dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip utama filsafat pendidikan."
DUNIA pendidikan tinggi di Indonesia sebentar lagi akan mengalami perubahan yang cukup besar dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permen tersebut salah satunya memuat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mewajibkan perguruan tinggi untuk memfasilitasi hak (dapat diambil atau tidak) mahasiswa untuk mengambil paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS di luar perguruan tinggi dan satu semester atau setara dengan 20 SKS di program studi (prodi) berbeda di perguruan tinggi yang sama.
Sebagai konsekuensi logis maka setiap prodi harus bersiap untuk melakukan perubahan kurikulum yang dapat mewadahi kegiatan pembelajaran sesuai yang diamanatkan Permen ini. Spirit utama Program MBKM ini adalah untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh para mahasiswa pada masa depan. Lebih spesifik, para mahasiswa disiapkan untuk menghadapi era industri 4.0. Secara eksplisit dikatakan, MBKM diluncurkan dengan tujuan meningkatkan link and match antara lulusan perguruan tinggi dan dunia usaha atau dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.
Tentu saja tujuan program ini sangatlah baik. Namun bukan berarti program ini lepas dari kelemahan dan memerlukan catatan kritis sebelum benar-benar diimplementasikan. Pertama, program MBKM berkesan sangat pragmatis. Penulis belum dapat menemukan muatan filsafat pendidikan yang kuat dalam program ini.
Jika mengutip pemikiran salah satu filsuf pendidikan Indonesia, Drijarkara, maka program ini memang betul sangat pragmatis. Salah satu pemikiran Drijarkara tentang pendidikan adalah sebagai berikut. “Konstruksi pengajaran tidak boleh didasarkan pada pandangan yang sekadar pragmatis, melainkan harus inkulturatif-progresif. Pandangan pragmatis hanya mempertimbangkan manfaat langsung dan konkret dari pengajaran. Sebagai contoh, prinsip link and match menekankan manfaat langsung produk pendidikan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang kehidupan. Sebaliknya, pandangan inkulturatifprogresif tentang pendidikan memandang kegiatan mendidik dan mengajar sebagai upaya memasukkan manusia muda ke dalam kebudayaan atau memasukkan kebudayaan ke dalam manusia yang belum dewasa, agar akhirnya dia mampu memanusia sendiri, membudaya sendiri, dan melaksanakan nilai-nilai sendiri sebagai manusia purnawan”. Pada bagian lain, pemikiran Drijarkara tentang pendidikan adalah sebagai berikut. “Pengajaran harus menghasilkan tenaga-tenaga yang penuh keberanian, tanggung jawab, dan cerdas”.
Dengan hal ini, Driyarkara hendak menegaskan, kecakapan manusia tidak boleh hanya berupa kacakapan mekanis dan teknis, melainkan harus juga dijiwai dengan keberanian dan tanggung jawab. Keberanian membuat orang mengerjakan atau menggeluti sesuatu secara total atau tidak setengah-setengah serta berani mengambil keputusan sesuai keyakinan dan kewenangannya. Bertanggung jawab berarti berdiri sendiri. Rasa tanggung jawab dan keberanian merupakan modal penting untuk menghadapi masifikasi dan homogenisasi atau penyeragaman, bahaya menghilangkan kepribadian manusia di balik berbagai bentuk komunalitas. Kecerdasan mencakup penguasaan secara agresif dan dinamis atas aneka objek dan peristiwa yang kita pelajari atau hadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sesuatu yang bermakna dan berguna (dikutip oleh Supratiknya, 2014).
Segitiga Kompetensi
Mengapa muatan filsafat pendidikan seakan lepas dari Program MBKM ini? Salah satu dugaan penulis adalah karena tim penyusun program ini memang tidak ada satu pun yang berlatar belakang filsafat pendidikan. Hampir semua tim penyusun berlatar belakang ilmu eksata. Untuk itu, jika program ini akan diimplementasikan, sebaiknya perguruan tinggi mengolahnya kembali dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip utama filsafat pendidikan, yang secara faktual mungkin semakin ditinggalkan dalam praktik pendidikan tinggi kita. Dalam perspektif yang lebih baru, Haryatmoko (2020) menyatakan, untuk menghadapi tantangan disruptif-inovatif, diperlukan segitiga kompetensi profesional, yaitu kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi komunikasi. Menurut penulis, Program MBKM lebih memfokuskan hanya di kompetensi teknis. Kedua, program ini mengandaikan atau berasumsi bahwa para mahasiswa kita telah memiliki kemandirian yang tinggi. Asumsi ini memunculkan gagasan para mahasiswa dapat belajar secara merdeka melalui berbagai matra dan tidak hanya terbatas di lingkungan program studinya.
Terdapat delapan kegiatan di luar prodi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, antara lain magang/praktik kerja, proyek kemanusiaan dan kegiatan wirausaha. Asumsi ini tentu saja baik. Apalagi jika merujuk pada teori tugastugas perkembangan dari Robert J Havighurst. Dalam teori tersebut seseorang yang telah memasuki usia remaja akhir diharapkan telah memiliki kemandirian. Namun menurut Havighurst sendiri, tugas perkembangan seseorang sangat dipengaruhi salah satunya oleh faktor budaya. Secara empirik, menurut pengalaman penulis, mahasiswa kita belum sepenuhnya memiliki kemandirian yang tinggi. Bukan salah mereka. Namun secara kultural budaya kita “belum mengizinkan” para mahasiswa untuk memiliki kemandirian yang penuh.
Hal ini bukan soal baik atau buruk, namun memang budaya masyarakat kita yang kolektivis “menghendaki” demikian. Maka jika MBKM ini sungguh diimplementasikan, para dosen harus bekerja keras untuk mendampingi dan mengawal para mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Yang lebih penting lagi, para dosen harus membantu mahasiswa merefleksikan pengalaman-pengalaman yang diperolehnya agar dapat menjadi pembelajaran bagi dirinya secara efektif.
Metode reflektif ini akan mengajak mahasiswa untuk berpikir analitis-kritis atas semua pengalaman yang diperolehnya dalam Program MBKM. Haryatmoko (2020) menekankan, kemampuan berpikir analitis-kritis inilah yang akan membantu para lulusan menghadapi dunia yang cepat berubah. Jika proses refleksi ini tidak dilakukan, mungkin saja Program MBKM hanya akan menjadi “pelarian” para mahasiswa dari segala hiruk pikuk dan rutinitas pengajaran di prodinya. Ketiga, Program MBKM mengandaikan bahwa semua mitra yang akan bekerja sama dalam program ini telah memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang telah diamanatkan. Realita di lapangan sering kali berbeda. Misalnya kelompok masyarakat, organisasi atau perusahaan yang menjadi tempat magang/ praktik kerja atau proyek kemanusiaan sering kali tidak memiliki “irama” yang senada. Abatnya, para mahasiswa magang sering kali hanya akan menjalankan tugas-tugas administratif selama proses tersebut. Untuk itu, perguruan tinggi harus sangat selektif dalam memilih mitra. Selain itu, juga diperlukan dialog yang intens untuk menyamakan “irama akademik” sehingga tujuan baik dari program ini tidak melenceng. (40)
►Suara Merdeka 16 Desember 2020 hal. 4
https://www.suaramerdeka.com/news/opini/249786-catatan-kritis-program-mbkm