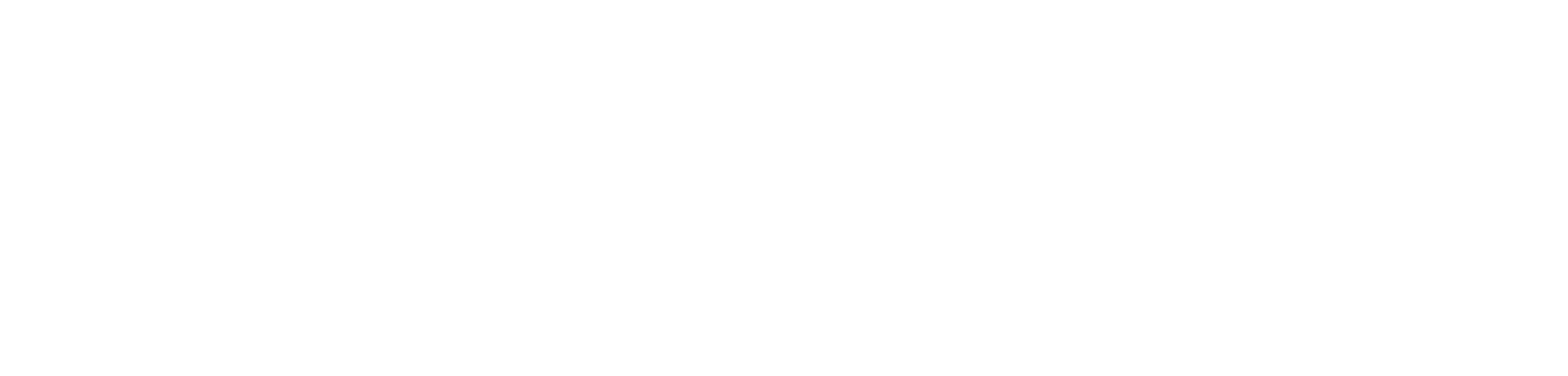Oleh ANDREAS LAKO
Profesor Machael Levitt (pemenang Nobel bidang biofisika tahun 2013) menyatakan, ”lockdown” seharusnya tak perlu dilakukan sejumlah negara karena hanya akan menutup roda perekonomian dan melahirkan kekalutan kesehatan.
Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar dan meninggal akibat Covid-19 di sejumlah provinsi, muncul desakan dari sejumlah kalangan agar Presiden Jokowi melakukan lockdown negara. Sejumlah kepala daerah juga meminta Presiden mengizinkan mereka melakukan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Sepintas, desakan itu bagus. Namun, apabila ditelaah lebih jauh, desakan itu tampaknya tidak didasarkan pada hasil analisis yang cermat terhadap semua aspek yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan lockdown atau karantina wilayah. Karena itu, akan sangat berisiko tinggi apabila Presiden Jokowi menuruti desakan itu.
Mengapa? Karena, dalam melakukan lockdown negara atau karantina suatu wilayah, pertimbangan aspek penanganan Covid-19 dengan aspek kemampuan ekonomi daerah dan aspek-aspek kemanusiaan harus diletakkan dalam satu tarikan napas. Tanpa perhitungan cermat terhadap semua aspek itu, lockdown atau karantina wilayah hanya akan menimbulkan banyak mudarat dibandingkan manfaatnya.
Bumerang ”lockdown”
Desakan sejumlah pihak agar Presiden segera melakukan lockdown negara sama seperti yang sudah dilakukan sejumlah negara tampaknya karena panik dan latah. Mengapa?
Karena, dari sisi kepentingan negara, Presiden Jokowi tak mungkin melakukan lockdown karena konsekuensi dan risiko-risiko ekonomi, sosial, politik, dan keamanannya sangat besar. Dari sisi keuangan (APBN), pemerintah pusat tak mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat selama masa lockdown. Secara ekonomi, Indonesia juga tak bisa mandiri selama lockdown karena kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga dan dunia usaha serta pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada impor dari negara-negara lain yang juga sedang terkena Covid-19.
Selain itu, lockdown justru jadi bumerang karena tingkat kegagalannya tinggi. Sejumlah negara yang sudah melakukan lockdown ternyata mengalami kegagalan serius. Misalnya, setelah memberlakukan lockdown (9/3/2020), kematian akibat Covid-19 di Italia justru melonjak drastis dari 463 orang menjadi 11.591 orang (30/3/2020). Per 4 April, yang meninggal di Italia sudah 14.681 orang.
Di Spanyol yang mulai lockdown pada 12 Maret 2020, kematian akibat Covid-19 melonjak dari 831 menjadi 7.340 orang (31/3/2020 dan per 4 April menjadi 11.198 orang. Negara-negara Eropa yang lain yang melakukan lockdown, seperti Perancis dan Inggris, juga bernasib sama.
Sementara lockdown parsial yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara bagiannya juga bernasib lebih buruk. Jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 sudah 163.807 orang per akhir Maret dan 277.522 per 4 April, tertinggi di dunia. Jumlah yang meninggal akibat Covid-19 melonjak drastis dari 453 orang (19/3/2020) menjadi 2.948 orang per 31 Maret dan 7.403 orang per 4 April. Menyadari kegagalan itu, Presiden Trump (28/3/2020) membatalkan pemberlakuan lockdown kota New York dan sejumlah negara bagian AS. Seorang ibu mengenakan masker saat berbelanja di Pasar Modern BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (4/4/2020). Pandemi Covid-19 membuat warga mengenakan masker dalam aktivitas sehari-hari sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.
Nasib lebih serius dialami India. Sejak hari pertama lockdown (24/3/2020), terjadi kekacauan secara nasional. Pemerintah India pun kewalahan menghadapi berbagai konsekuensi dan risiko dari lockdown. Mencermati kegagalan sejumlah negara, keputusan Presiden Jokowi yang tak menerapkan lockdown, tapi menempuh cara-cara lain yang lebih manusia (soft) sudah tepat dan patut diapresiasi.
Hasil studi saya juga menunjukkan tren persentase kenaikan jumlah orang yang terpapar Covid-19 kian menurun sejak minggu ketiga hingga akhir Maret 2020. Trennya menurun dari kisaran 20-36 persen (17-21 Maret) ke kisaran 10-18,3 persen (22-30 Maret). Pada 28-30 Maret 2020, penurunannya bahkan sudah mencapai kisaran 10-12 persen. Ini menunjukkan daya papar Covid-19 kian mereda.
Risiko karantina
Desakan sejumlah kepala daerah agar Presiden Jokowi mengizinkan mereka melakukan karantina wilayahnya tampaknya juga tidak cermat. Alasannya, karena karantina wilayah berpotensi besar menimbulkan berbagai masalah serius bagi masyarakat luas dan membebani pemerintah pusat dibandingkan efektivitasnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mengapa?
Pertama, dari struktur ekonomi rakyat, mayoritas mata pencarian penduduk dari wilayah-wilayah yang meminta karantina sangat bergantung pada sektor-sektor informal sehingga kelangsungan hidup dari mayoritas masyarakatnya akan sangat terganggu apabila dilakukan karantina wilayah.
Pemerintah daerah juga tak akan sanggup memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Ini karena mayoritas provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air tak memiliki kemampuan keuangan daerah yang memadai. Mereka masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Tanpa adanya dukungan dana dari pemerintah pusat, tidak ada satu daerah pun yang akan mampu melakukan karantina wilayah secara mandiri lebih dari satu pekan.
Kedua, dari struktur perekonomian provinsi atau kabupaten/kota yang meminta karantina, tak ada satu pun yang bisa mandiri. Bahkan, lebih dari 90 persen pemda di Indonesia tak ada yang bisa mandiri. Semuanya sangat bergantung pada ”kemurahan hati” dari pemerintah pusat dan dukungan relasi ekonomi dari daerah-daerah lain. Dari sisi permintaan, proporsi permintaan untuk konsumsi rumah tangga sangat mendominasi perekonomian suatu daerah.
Impor dari negara-negara lain dan juga dari daerah-daerah lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sangat besar dan jauh lebih besar dibandingkan ekspornya. Impor juga dipakai untuk keperluan pengeluaran pemerintah dan kebutuhan industri dalam menghasilkan barang/jasa untuk masyarakat.
Oleh karena itu, apabila dilakukan karantina wilayah, pasokan barang/jasa untuk kebutuhan masyarakat dari daerah-daerah lain akan terganggu. Demikian pula aktivitas ekonomi dunia usaha dalam menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat luas akan lumpuh. Daerah-daerah lain di sekitarnya belum tentu akan memasok barang/jasanya karena mereka juga membutuhkannya. Akibatnya, ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat akan langka.
Harga-harga barang kebutuhan pokok akan melonjak drastis. Risiko-risiko seperti kelaparan, kekalutan, kekacauan, dan melemahnya daya tahan masyarakat sehingga rentan terhadap Covid-19 dan berbagai penyakit lainnya justru akan besar.
Ketiga, dari sisi penawaran, struktur ekonomi dari mayoritas daerah di Tanah Air rapuh. Mayoritas kota-kota besar juga tidak mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mereka sangat bergantung pada pasokan dari daerah-daerah lain. DKI Jakarta, misalnya. Meski APBD-nya sangat besar (Rp 87,95 triliun), tetapi kontribusi sektor pertanian hanya 0,08 persen. Ketergantungan DKI terhadap Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan daerah-daerah lain serta impor dari negara-negara lain sangat tinggi.
Seandainya Gubernur DKI nekat melakukan karantina, sementara dukungan dari pemerintah pusat dan sejumlah provinsi di Ja
wa kurang, karantina DKI Jakarta hanya akan bertahan beberapa hari. Risiko terburuknya adalah terjadinya penjarahan dan kerusuhan massal karena masyarakat kalut dan kalap akibat terancam kelangsungan hidupnya.
Hindari karantina
Dari uraian di atas, baik lockdown maupun karantina wilayah bukanlah solusi terbaik untuk mencegah dan meminimalkan dampak-dampak negatif Covid-19. Opsi tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, komplikasi masalah, dan risiko serius. Selain akan menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan sangat mahal biayanya, dua opsi tersebut juga berpotensi meningkatkan daya papar dan daya bunuh Covid-19 serta radikalisme masyarakat yang sangat merugikan masyarakat luas, daerah dan negara.
Terkait risiko itu, Profesor Machael Levitt (pemenang Nobel bidang biofisika tahun 2013) menyatakan, lockdown seharusnya tak perlu dilakukan sejumlah negara karena hanya akan menutup roda perekonomian dan pada gilirannya akan melahirkan kekalutan kesehatan itu sendiri. Hal ini disebabkan tingginya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan untuk hidup.
Pernyataan Levitt itu tepat. Setelah lockdown, jumlah penduduk yang terpapar dan meninggal akibat Covid-19 di Italia, Spanyol, Perancis, Inggris, AS, dan lainnya malah naik drastis. Sebaliknya, sejumlah negara yang tidak lockdown justru sukses menekan laju paparan Covid-19.
Oleh karena itu, solusi terbaik untuk mencegah meluasnya Covid-19 adalah semua kepala daerah dan semua pihak serius menindaklanjuti Instruksi Presiden tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil (PSBB-DS). Penerapan instruksi itu tidak akan menghabiskan dana APBN dan APBD yang sangat besar. Juga tidak akan menimbulkan kepanikan masyarakat luas. Potensi terjadinya radikalisme sosial juga kecil. Singkatnya, biaya dan risikonya jauh lebih kecil dibandingkan karantina wilayah.
Syaratnya, pelaksanaannya tidak boleh gegabah, tapi dipersiapkan secara cermat dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan pemda di sekitarnya. Panglima pelaksananya di setiap provinsi adalah gubernur sehingga para bupati/wali kota tidak boleh bertindak semaunya dalam menerapkan PSBB-DS karena akan menyebabkan masyarakat luas bingung dan panik.
(Andreas Lako, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata, Semarang)
►Kompas 7 April 2020, https://kompas.id/baca/opini/2020/04/07/hindari-lockdown/