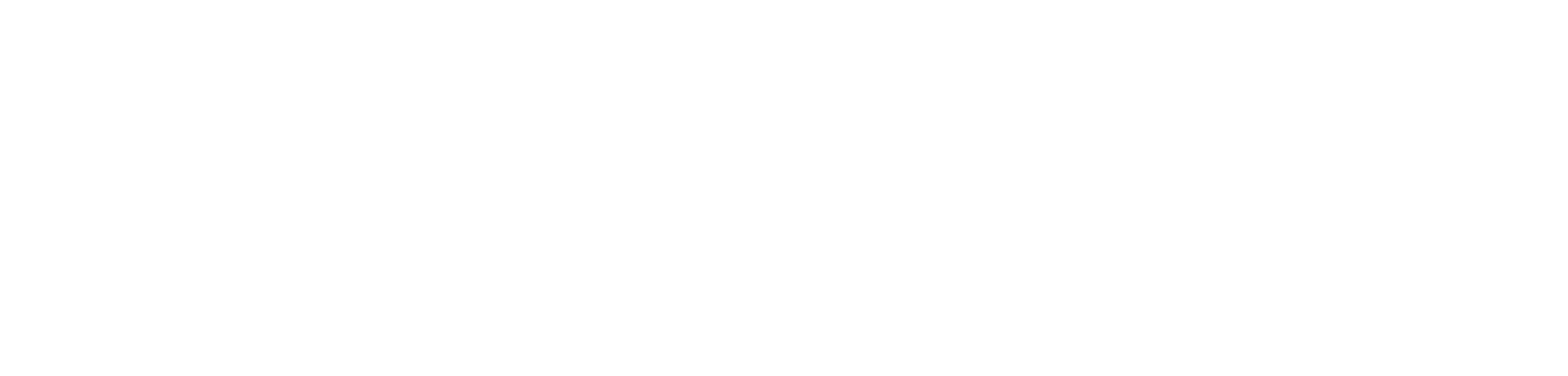Oleh: Antonius Maria Laot Kian
Dalam kenyataan postmodernisme, kerentanan akan adanya perpecahan bangsa merupakan momok yang menakutkan. Pertarungan antara berbagai “ideologi” dalam bingkai negara kesatuan RI menciptakan krisis ingatan tentang persatuan. Kita seperti ditabrak oleh “truk” bermuatan postmodern yang menciptakan hilang ingatan (retrogade amnesia) bagi sebagian kita, atau malah bagi sebagian yang lain menuju kelainan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (alzheimer) berkepanjangan. Memang benar pendapat Farouk Muhammad dalam Opini KOMPAS (Selasa, 31 Januari 2017) yang menyitir pudarnya paham kebangsaan oleh karena kondisi ekonomi yang sulit, sosial politik yang tidak kondusif, hukum yang tidak tegas, dan keamanan yang rentan. Akan tetapi, dentuman psikologis yang lebih luas dari faktor-faktor tersebut ialah kecelakaan “cepat lupa” yang membuat kita mengagung-agungkan perbedaan sebagai “agama” (baca: berhala) baru.
“Agama (berhala) perbedaan” kemudian memandang aku sebagai aku, bukan aku sebagai engkau. Kondisi ini mungkin akan membuat Demokkritos, filsuf Yunani ribuan tahun yang lalu, mengejek kita karena baginya, keseimbangan semesta dibangun dari atom-atom (unsur-unsur) yang berbeda namun saling kait-mengkait dan melengkapi. Bila demikian, kecelakaan cepat lupa kita terjadi karena kita terlalu sibuk memisah-misahkan “atom-atom” pribadi seturut homogenitas; kita terlalu sibuk mendeskripsikan identitas ke-aku-an dan membandingkannya dengan aku yang lain; kita terlalu menjejali diri kita dengan budayaku, agamaku, pekerjaanku, rumahku, dan aneka ke-aku-an yang lain. Padahal, bila kita ingat, pengakuan ke-aku-an hanya akan ada bila ada aku yang lain yang mengakui ke-aku-an kita.
Perlu Mengingat
Memento! Ingatlah! Berabad-abad yang lalu, Tertullianus (160-220), dalam Apologeticus menulis dengan indah, “Respice post te! Hominem te memento!”, untuk memberikan peringatan terhadap kemegahan imperium Romawi, bahwa mereka hanyalah manusia belaka. Beratus-ratus tahun kemudian, nada dasar “mengingat” ala Tertullian, diulangi lagi oleh romantisisme Mazhab Frankfrut di bawah pemikiran Walter Benjamin (1892-1940), tentang memento passionis. Memento passionis dalam bingkai dialektika negatif, mengajak manusia untuk mengingat narasi sejarah yang diguratkan dalam penderitaan. Dalam masa yang sama, filsuf Prancis Maurice Halbwachs (1877-1945) menciptakan mahakaryanya La Mémoire collective, dengan memberikan tekanan pada ingatan bersama yang diproduksi oleh “keluarga” (baca: identitas konseptual yang diwariskan dari generasi ke generasi). Tidak cukup sampai di situ! Di tahun 2000, sutradara film Christopher Nolan mendedikasikan makna “mengingat” dalam film penuh puzzle berjudul “memento”, yang mengafirmasi tindakan mengingat Leonard Shelby melalui tato di sekujur tubuhnya. Dan kini, aforisma Goenawan Muhammad, dalam Pagi dan Hal-hal yang Dipungut Kembali, memberi kita dasar bagi tujuan mengingat: “mengingat kesewenang-wenangan masa lalu tak berarti dibelenggu masa lalu. Kita ingin memperbaiki masa depan”.
Mengapa perlu “mengingat”? Dalam beberapa pekan belakangan ini, kehidupan berkebangsaan kita dihantui oleh penyakit saling curiga yang akut, yang berujung pada keterpecahan antarkelompok masyarakat, keterpisahan antargolongan, yang membuat kita terpuruk pada stigmatisasi postmodern: pengagungan narasi kebenaran lokal! Setiap kelompok merasa dirinya paling benar, lalu secara tendensius menihilkan eksistensi kelompok lain. Celakanya, dalam pertarungan identitas kelompok semacam itu, kenisbian individu pun ikut merebak dalam kepercayaan semu suatu keramaian massa teknokratik (mobile vulgus) yang diciptakan oleh arus informasi teknologi dan komunikasi. Individu-individu Indonesia menjadi kehilangan identitas ke-Indonesia-annya karena dikuasai oleh berita-berita yang memecah-belah. Sukma homo homini socius seperti ditelan oleh arogansi kepentingan pribadi dan golongan. Tidak mengherankan bila Sang Presiden berkali-kali menyerukan agar mengingat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Mengingat” dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana “Jas Merah” Soekarno, adalah merenungkan kembali narasi-narasi agung yang dilahirkan dari rahim ibu pertiwi, merefleksikannya, dan menjadikannya tolok ukur untuk bermawas diri. Bila mengenang, bangsa kita pernah berjaya di bawah Sriwijaya pada abad ke-7; pun pula pernah menjadi penguasa maritim hingga ke Semenanjung Malaya di bawah Majapahit pada abad ke-14—demikian tutur Kakawin Negarakertagama. Kita perlu merayakan kembali ingatan-ingatan bersama semacam itu, yang secara historis melahirkan “nusantara”. Nusantara kita adalah nusantara yang berkoeksistensi: bahwasanya tidak ada Jawa bila tidak ada Sumatera; atau tidak ada Bali bila tidak ada Kalimantan; atau takkan dikenal negeri Sulawesi bila tidak diceritakan tentang Papua. Itulah ingatan identitas Indonesia yang harus dirayakan secara terus-menerus.
Dalam alur narasi di atas, “mengingat” tentang memori kejayaan persatuan Indonesia, akan memberikan warna yang menghidupkan. Bangsa ini tidak lahir dari fundamentalisme agama tertentu, juga tidak diwariskan dari primordialisme suku tertentu. Bangsa ini dilahirkan dari keberagaman yang memerdekakan, yaitu keberagaman yang menciptakan senyum tulus antargenerasi; keberagaman yang menciptakan nama Indonesia—tegasnya: peradaban Indonesia!
Merawat Ingatan
Barangkali kita sepakat bahwa sejarah adalah penciptaan memori untuk generasi masa depan. Dalam konteks itu, sangatlah penting membangun peradaban yang mempersatukan melalui tindakan merawat ingatan. Adalah Joziaas van Aartsen, seorang walikota Den Haag, meresmikan Munirpad di dekat Salvador Allende Straat, hanya untuk mengingat seorang Munir; lebih dari itu tentu saja mengingat perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan merawat ingatan semacam itu mereproduksi kenangan bersama tentang nilai kemanusiaan yang mempersatukan peradaban. Merawat ingatan adalah merayakan yang ada dengan yang “tak ada”, yaitu timbunan ingatan, demikian kata film Surat dari Praha.
Memento! Ingatlah! Seruan ini menuntut para pencipta sejarah bangsa untuk membangun “ritual” persatuan dalam heterogenitas. Generasi muda perlu dididik untuk terus-menerus mencintai heterogenitas sebagai perayaan bersama. Generasi muda perlu diingatkan terus-menerus bahwa heterogenitas adalah awal kehidupan. Bukankah apa yang homogen cenderung imoral? Memento, ingatlah: persatuan itu sederhana, yaitu dengan mengingat bahwa kita pernah bersatu, di suatu masa, di suatu waktu.
–Antonius Maria Laot Kian, Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata
https://m.ayosemarang.com/read/2020/01/31/51519/indonesia-memento