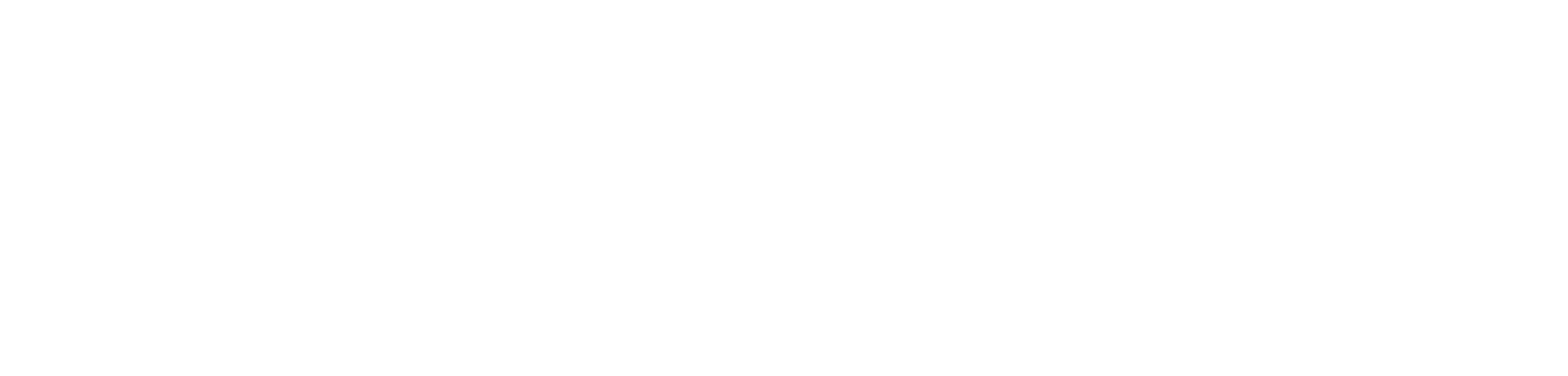Oleh : Budi Widianarko
"Sebenarnya apa yang sedang terjadi, baik di Indonesia maupun Amerika saat ini adalah matinya retorika. Para pemimpin publik yang berkuasa dan berpengaruh saat ini tidak memiliki kemampuan retorika."
SALAH satu simpulan menarik dari perbincangan tiga budayawan —Ridwan Saidi, Arswendo Atmowiloto, dan Agus Noor— di layar CNN Indonesia (15/4) adalah rendahnya mutu perdebatan politik di negeri ini. Ridwan Saidi bahkan menyebut perdebatan antarpolitikus yang berseberangan saat ini sangat dangkal dibandingkan dengan perdebatan di sidang Dewan Konstituante pada 1950-an. Kecenderungan penggunaan kata-kata yang kasar dan merendahkan menunjukkan kedangkalan itu.
Menurut ketiga budayawan tersebut, masyarakat mengharapkan sajian adu argumentasi yang lebih berbobot. Ternyata apa yang tengah berlangsung di sini tidaklah unik. Pada hari-hari ini, warga Amerika Serikat menjadi saksi sebuah sajian cara bertutur yang ”aneh” dari sang Presiden sendiri, Donald Trump. Dalam wawancara di MSNBC (September 2017), John McWhorter —guru besar linguistik Universitas Columbia— menyebut Donald Trump punya gaya bicara yang paling unik, berbeda dari semua presiden yang pernah dimiliki AS.
Menurut McWhorter, Trump suka menggunakan gaya bahasa kasual bahkan di forum-forum yang mestinya menuntut cara bicara yang formal. Bahkan McWhorter mengatakan, kemampuan linguistik Trump memang tidak berkembang sehingga tidak mampu empan papan dalam berbicara.
Padahal, lanjut McWhorter, dalam masyarakat primitif yang belum tersentuh pendidikan pun dikenal unggah-ungguh berbahasa. Dalam setiap peradaban juga dikenal bahasa tinggi dan rendah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, baik di Indonesia maupun Amerika saat ini adalah matinya retorika. Para pemimpin publik yang berkuasa dan berpengaruh saat ini tidak memiliki kemampuan retorika. Gejala ini sebenarnya telah dikaji oleh Elvin Lim (2008) dalam bukunya The Anti Intellectual Presidency – The Decline of Presidential Rhetoric from George Washington to George W Bush.
Seperti tecermin dari judulnya, si penulis menggambarkan bahwa telah terjadi kemerosotan mutu retorika Presiden AS dari masa ke masa. Sulit disangkal bahwa salah satu institusi yang ikut bertanggung jawab atas kemerosotan mutu retorika ini adalah perguruan tinggi. Dibelenggu oleh tujuan-tujuan yang semakin pragmatis seperti korporatisasi, komersialisasi, dan penghambaan kepada pasar kerja, perguruan tinggi kontemporer kesulitan untuk menghasilkan sosok manusia utama seperti yang diidealkan oleh universitas pada awal kelahirannya.
Retorika
Kemerosotan mutu retorika yang ditandai oleh kedangkalan dalam argumentasi boleh jadi karena retorika hanya diajarkan di jurusan-jurusan tertentu, seperti bahasa, komunikasi, dan yang terkait.
Padahal, dulu retorika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di universitas. Di universitas klasik pada abad pertengahan, semua mahasiswa mempelajari dua rumpun pembelajaran utama, yaitu trivium dan quadrivium.
Trivium terdiri atas tiga pelajaran dari rumpun ilmu bahasa, yaitu tata bahasa, logika, dan retorika (grammar, logic, rehetoric). Adapun quadrivium mencakup empat pelajaran, yaitu aritmatika, geometri, astronomi, dan musik (arithmatic, geometry, astronomy, and music). Menurut Walter R¸egg (2004), penyunting buku A History of the University in Europe, dalam tatanan pendidikan tinggi modern hanya program liberal art yang mengajarkan trivium dan quadrivium kepada seluruh mahasiswa dan sering kali dengan tambahan tiga pelajaran dari rumpun filsafat, yaitu fisika, etika, dan metafisika. Mengutip James MacLachlan (2004) dalam buku Children of Prometheus – AHistory of Science and Technology, dengan mempelajari tata bahasa, mahasiswa belajar tentang penyusunan kata-kata secara tepat untuk membentuk kalimat.
Logika mempelajari bagaimana menyusun kalimat secara tepat dalam membentuk argumen. Adapun retorika mengajarkan bagaimana menyusun sejumlah argumen secara tepat untuk membentuk wacana.
Pengajaran trivium umumnya bertumpu pada para filsuf Yunani, khususnya Cicero (106-43 SM) yang menuliskan karyanya dalam bahasa Latin. Di jurusan selain bahasa dan komunikasi sebenarnya jejak retorika dapat dijumpai dalam beberapa mata kuliah, seperti penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Namun karena sifatnya yang lebih berorientasi praktis, maka watak hakiki dari retorika cenderung terkubur. Retorika sering disalahtafsirkan sebagai susunan kata-kata kosong yang kadang memunculkan kesan gagah, elegan atau indah.
Pada hakikatnya, retorika adalah ilmu dan seni tentang bagaimana menulis dan berbicara yang baik dan memiliki daya persuasi. Pelajaran retorika membekali pesertanya dengan keterampilan utama dalam pembelajaran dan pendidikan tingkat tinggi, yaitu kemampuan untuk berpikir logis, mengenali argumen yang lemah atau salah, membangun argumen yang kuat tentang topik-topik kontroversial, dan mengatasi ketakutan untuk berbicara di muka umum. Singkatnya, retorika adalah penyusun utama pendidikan (tinggi) yang baik untuk semua jurusan atau program.
Tantangan Kampus
Lebih jauh, Walter R¸egg (2004) menyatakan, kapasitas retorik seseorang yang terungkap dari kememampuannya menemukan tajuk (subjek) menyusun argumen, mengembangkan wacana, dan membuat penilaian yang tepat tidak dapat dipelajari secara teoritik belaka.
Himpunan kemampuan itu harus dilatih dan dikembangkan melalui teori dan praktik secara seimbang, baik oleh pembelajar pemula maupun lanjut. Dengan kata lain, kampus adalah ”Kawah Candradimuka” untuk menggembleng pemahaman teori dan praktik retorika bagi insan akademiknya. Yang menjadi tantangan, pemerintah di banyak negara, termasuk di negeri ini, memilih pola masifikasi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi bukan lagi diperuntukkan bagi segelintir elite, melainkan untuk semua.
Pilihan ini bisa dikatakan tepat untuk sebuah negara berkembang dan yang relatif muda. Sebagai konsekuensinya, pendidikan tinggi terbebani oleh jumlah mahasiswa yang melimpah.
Ketika terhimpit beban ganda jumlah mahasiswa dan pragmatisme pasar maka sangat berat bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan cita-cita awalnya, yaitu membentuk sosok manusia utama.
Untuk menyikapi tantangan ini diperlukan kreativitas dari para pemimpin perguruan tinggi, termasuk para pemuka intelektual, untuk memanfaatkan dan menciptakan ruang-ruang perjumpaan intelektual di setiap sudut kampus.
Penampilan monolog intelektual ala TEDx Talks menarik untuk diadopsi oleh kampus. Begitu pula acara perdebatan intelektual berupa diskusi, seminar, sarasehan, dan sejenisnya yang membahas wacana publik aktual harus terus dihidupkan dan dirawat. Semua kegiatan itu harus diupayakan menjangkau segenap insan akademik, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan yang penting, gairah ber-retorika itu harus dibalut dengan kesukacitaan para dosen dan mahasiswanya . Itulah hakikat universitas magistrorum et scholarium. Saran ini mungkin berkesan seperti mimpi, tetapi bukankah sudah selayaknya jika perguruan tinggi dihuni oleh mahluk yang masih mau bermimpi?
—Budi Widianarko, dosen Unika Soegijapranata, guru besar tamu di Providence University Taiwan.
►Suara Merdeka 5 Mei 2018 hal. 4, https://www.suaramerdeka.com