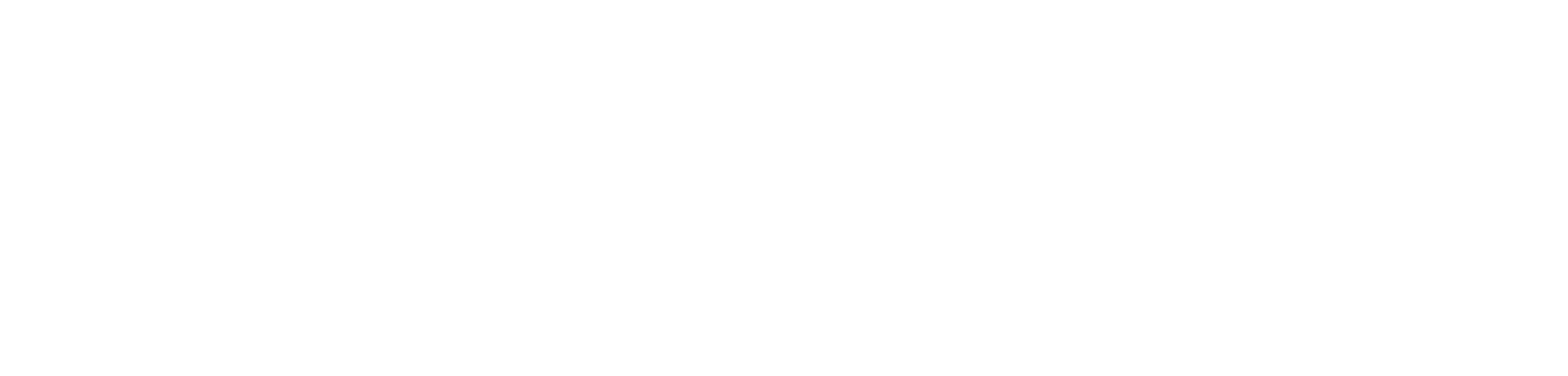Oleh: Dr Rudyanto Soesilo
FENOMENA maraknya kemunculan berbagai ”kerajaan” akhir-akhir ini merupakan perwujudan dari apa yang ada dalam bawah sadar masyarakat kita. Yaitu ketidakberdayaan diri, sembari mencari pemimpin yang kiranya mampu membantu dirinya, yang tentu harus lebih berdaya dari dirinya. Pemimpin yang dulu diistilahkan sebagai ”sakti mandraguna”, yang kurang lebih sekarang adalah memiliki pengetahuan dan kecerdasan di atas rata-rata pengikutnya. Fenomena ini merupakan manifestasi dari budaya paternalistik, yang kemudian mengejawantah pada fenomena kerajaan, keraton, empire abalabal, yang muncul bagaikan cendawan di musim banjir ini. Nah apa yang ada dalam bawah sadar itu, nantinya berujung pada porsi pendidikan yang diterima masyarakat kita.
Fenomena keraja-rajaan ini sebetulnya merupakan tandingan dan potret dari penyelenggaraan demokrasi (demokrasi feodalistis) yang sekarang dipraktikkan. Para kontestan banyak yang merasa dan bergaya bak seorang raja atau ratu dalam bungkus pilkada ataupun ”pilpil” lainnya. Keriuhrendahan kontestasi dalam nuansa lokal merupakan ajang pamer kedigdayaan. Sering yang ditampilkan adalah ajang pamer kharisma, kadang dalam bentuk sebaran politik uang dalam berbagai bungkus kamuflasenya. Institusi resmi semacam partai politik bahkan memanfaatkan alam bawah sadar rakyat pemilih itu, dengan menampilkan figur-figur terkenal, para artis yang disukai masyarakat misalnya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan.Fenomena demokrasi keraja-rajaan ini pada akhirnya juga bermuara pada upaya pembentukan dinasti-dinasti. Inilah kenyataan demokrasi kita.
Dahulu Ken Arok, seorang penggawa yang notabene pemuda desa biasa, berhasil menggulingkan Tunggul Ametung, lalu menikahi istrinya, Ken Dedes, lantas naik takhta menjadi penguasa di situ. Bahkan ia mengangkat dirinya menjadi raja. Upayanya bermuara pada pendirian Wangsa Rajasa, sebuah dinasti baru.
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para pendiri kerajaan, keraton dan empire abal-abal di era demokrasi ini, sama saja dengan gerak langkah Ken Arok dan pendiri-pendiri dinasti waktu itu. Ada sosok pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan di atas rata-rata pengikutnya. Ada khalayak yang kemudian menjadi pengikut, ada para penggawa, maka terbentuklah sesuah sistem feodalistis dengan si pemimpin yang menjadi rajanya (monarch).
Para monarch memberi harapan, rasa aman (semu?). Sebagai timbal baliknya para pengikut kemudian harus membayar upeti (iuran). Dalam demokrasi keraja-rajaan, para bakal calon pemimpin berkampanye memoles kedigdayaan mereka, menabur harapan dan rasa aman dengan unjuk kehebatan, kebisaan, kadang dihiasi taburan politik uang.
Mudah Gumun
Banyaknya masyarakat yang terpedaya investasi bodong, sebenarnya merupakan fenomena dengan akar yang sama, yaitu bawah sadar masyarakat yang fatalistik, sehingga mudah gumun (heran) terhadap penampilan polesan dari sosok ”sok” pemimpin atau ”sok” pemberi harapan.
Lalu faktor apa yang bisa menghindarkan pembentukan bawah sadar fatalistik ini? Pendidikan menjadi hal yang mutlak untuk membentuk bangsa. Lantas, pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang berdasarkan kepatuhan belaka menciptakan fatalisme (ajaran atau paham bahwa manusia dikuasai oleh nasib) dalam masyarakat. Padahal sebenarnya masyarakat senang dan mengagumi kecerdasan, kekritisan, inovasi, dan lainlain. Akan tetapi sebatas kagum untuk mematuhi.
Demokrasi sebenarnya mengasumsikan kondisi masyarakat yang egalitarian, setara, termasuk kadar intelektualitasnya. Selama belum setara, ada celah pemisah antara pemimpin dan khalayak.
Selama pendidikan masih bertujuan mendapatkan kepatuhan yang sebenarnya merupakan bentuk penindasan kesadaran, atau pendidikan yang hanya untuk membentuk rakyat yang patuh dan manut, hanya membentuk massa yang mau disuruh apa saja.
Adapun bagi kelas pemimpin khalayak ini, mereka mendapatkan fasilitas dan sistem pendidikan yang seharusnya. Dalam ketimpangan sistem pendidikan seperti ini, kita akan menuai fenomena masyarakat yang selalu mencari ”raja-rajaan” baik yang resmi melalui pilkada, ataupun yang abal-abal. (54)
— Dr Rudyanto Soesilo, Dosen Filsafat dan Etika, Pascasarjana dan Program Doktor Ilmu Lingkungan, Unika Soegijapranata, Semarang.
►Suara Merdeka 11 Februari 2020 hal. 6
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/217000/keraja-rajaan-dalam-demokrasi