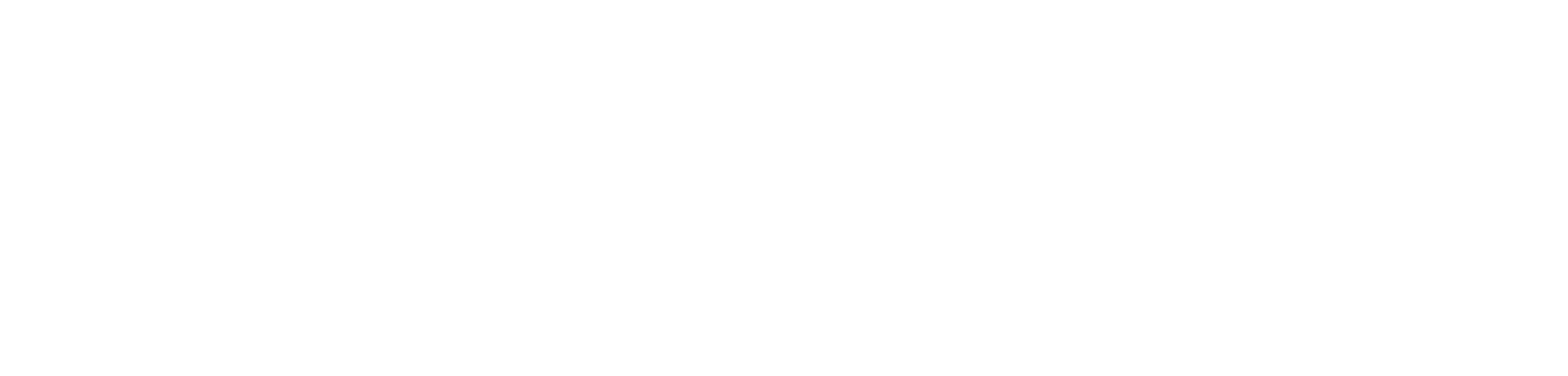Oleh: Amrizarois Ismail SPd MLing, dosen Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Unika Soegijapranata Semarang.
PPKM Darurat diberlakukan untuk Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli 2021, hingga diperpanjang dua kali dan akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021.
Hal tersebut menjadi sebuah alarm bagi masyarakat untuk kembali bersiap mengencangkan ikat pinggang, menahan diri untuk tidak bisa memaksimalkan pekerjaan, yang berarti juga ancaman bagi keberlangsungan kehidupan keluarga.
Bukan tanpa dasar, hal itu sangat beralasan melihat berbagai pemberitaan di media hingga kejadian di lingkungan sekitar yang menunjukkan banyak anggota masyarakat yang mengeluh rugi akibat pengetatan aturan pembatasan sosial dalam PPKM Darurat, yang seolah-olah diterjemahkan sebagai pelarangan mutlak untuk aktivitas usaha, terutama bagi pedagang kecil yang biasa mengandalkan pendapatan harian dengan berjualan.
Bagai mana tidak, pelarangan makan di tempat dan pembatasan jam berjualan hingga jam 8 malam tentu mengakibatkan penurunan omset harian. Hal itu diperparah dengan represivitas petugas penegak aturan PPKM di lapangan, seperti adanya perampasan barang dagangan, perlengkapan warung, penyiraman barang dagangan dengan pemadam kebakaran, hingga tindak kekerasan aparat terhadap pelaku usaha.
Berbagai kegaduhan dalam PPKM Darurat tersebut menjadi hasil yang berlawanan dengan apa yang diharapkan pemerintah, yaitu terciptanya ketenangan dan ketertiban, sehingga angka Covid-19 dan ketakutan masyarakat dapat dikendalikan.
Penambahan waktu PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021 tentu akan menambah pula rasa waswas masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang usaha hariannya lumpuh dalam PPKM ini dan alhasil sudah bisa ditebak akan ada kegaduhan dalam penegakan aturan di lapangan seperti saat ini.
Lalu pertanyaannya, mengapa upaya mitigasi bencana kesehatan bisa berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat? Pertanyaan tersebut seharusnya tidak perlu muncul, bila kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini menjadi penyebab kegaduhan betul-betul diperhatikan dan diberi solusi oleh pemerintah.
Bantuan sosial menjadi solusi yang belakangan dikabarkan akan diberikan, namun kesan terlambat dan risiko ketidakmerataan menjadi penyebab mengapa masih diperlukan jaminan mutlak subsidi pemenuhan kebutuhan selama PPKM, yang sejatinya merupakan karantina kesehatan.
Persoalan karantina kesehatan sebetulnya bukan hal yang baru. Pasalnya, negara kita sebelum pandemi Covid-19 juga pernah mengalami bencana kesehatan seperti Sars dan Flu Burung, hingga negara sudah memiliki payung hukum untuk mengantisipasi kejadian serupa, yaitu UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.
Dalam UU tersebut, tepatnya pada Pasal 55, dijelaskan bahwa negara boleh saja melakukan pembatasan total kegiatan masyarakat demi kepentingan kesehatan, dengan catatan hak kebutuhan sehari-hari masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sayangnya pemerintah tidak pernah menggunakan diksi karantina wilayah, meskipun sejatinya kebijakan pembatasan sosial yang pernah diambil mulai PSBB hingga PPKM Darurat secara praktik hampir serupa dengan konsep karantina. Terlebih saat PPKM Darurat ini banyak akses jalan umum, jalan tol, moda transportrasi, bahkan kegiatan ekonomi yang dibatasi oprasionalnya, sehingga masyarakat pun seolah-olah tidak diperbolehkan untuk melakukan pergerakan layaknya karantina.
Seperti kehabisan modal, tampaknya pemerintah saat ini enggan memberlakukan aturan pembatasan sosial dengan diksi karantina wilayah, karena khawatir tidak mampu menanggung beban ekonomi untuk menghidupi rakyatnya.
Hal yang ironi, melihat sebelumnya pemerintah begitu mudah meneken utang untuk keperluan yang urgensinya bisa ditunda, contoh saja utang untuk infrastruktur hingga isu utang untuk keperluan pertahanan yang nilainya mencapai Rp 17 quadriliun (CNN Indonesia), dan kali ini merasa keberatan untuk melakukan spekulasi ekonomi untuk menjamin rakyatnya agar tidak mati kelaparan.
Pemusatan CSR
Apabila mau sedikit jeli dan bersusahpayah, sebetulnya Indonesia tidak kekurangan investor, para pengusaha parlente, hingga para tuan yang dijuluki sultan atas kekayaan yang mengeruk dari bumi Indonesia. Seharusnya pemerintah selaku pemegang hak otoritatif dalam hal apa pun mampu menunjukkan taringnya dengan memaksa perusahaan- perusahaan raksasa yang bercokol hidup dan kaya raya di bumi Indonesia untuk iuran, mencurahkan seluruh kemampuan filantropinya untuk membantu rakyat yang ada di sekitarnya, mungkin dengan konsep pemusatan corporate social responsibility (CSR).
Program CSR merupakan program filantropi atau kearifan sosial suatu perusahaan untuk masyarakat di sekitarnya dan diwajibkan olehnya sebagai imbal jasa terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, yang selama ini dilakukan secara parsial dan terpisah oleh masing-masing perusahaan dengan dana yang tidak sedikit.
Bayangkan saja bila dana yang ada digerakkan terpusat dan kolektif untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.
Potensi dana CSR dari perusahaan sejatinya tidak sedikit. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh Wakil Ketua Kadin Bambang Soesatyo sebagaimana dilansir detik.com bahwa potensi CSR pada tahun 2020 mencapai Rp 10 triliun, dan tentu jumlah itu belum termasuk dana CSR yang tidak ditunaikan.
Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum mengenai banyak perusahaan yang menghidar dari kewajiban penyaluran dana CSR. Potensi filantropil lain tentu masih banyak, misalnya para orang kaya dari berbagai kalangan, publik figur, dan artis-artis sultan.
Hal ini menjadi solusi alternatif apabila dalih jebolnya anggaran negara menjadi alasan pemerintah untuk enggan memberlakukan karantina wilayah. Pasalnya negeri ini tidak kekurangan potensi filantropi, dan pemerintah harus tegar dan galak untuk mengejarnya, terutama bagi yang berkewajiban. Jangan hanya bertaring saat menghadapi masyarakat, namun ompong ketika dihadapkan pada para tuan. Dan satu lagi, yang penting dananya jangan dikorupsi lagi.(37)
►https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04503652/main-diksi-dalam-hukum-karantina?page=all