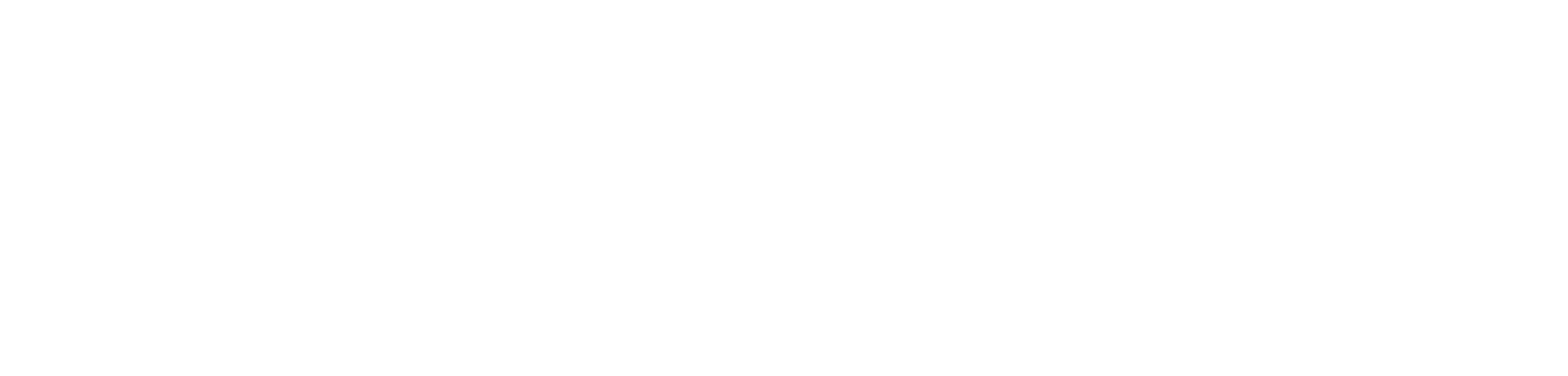Oleh: JC Tukiman Tarunasayoga, Ketua Dewan Penyantun Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata, Semarang
Bacalah bombang sebagaimana Anda mengucapkan goyang ataupun loyang, sedangkan bombong, ucapkanlah seperti Anda mengatakan Wong Gombong tidak sombong. Dari susunan konsonan itu, boleh saja Anda berseloroh mengatakan “Bambang bimbang lalu bambung” (nekat atau semau gue).
Bombang, di beberapa daerah dikatakan sebagai kebombang, berlaku untuk orang yang semula berpangkat, dan sebutlah saat itu memiliki tujuh asisten pribadi (ada yang ngurus kopor sendiri karena orang berpangkat itu sering pergi; ada yang ngurus sepatu sendiri karena memiliki berpuluh pasang padahal harus selalu mengilap kinclong.
Orang bombang utawa kebombang seperti itu, saat ini mung thela-thelo, buka lawang ya buka dhewe; nyemir sepatu ya nyemir dhewe; bahkan sangat boleh jadi saiki bali kathokan kolor maneh, kembali pakai celana kolor lagi ngumbah mobil dhewe, cuci mobil sendiri. Sarwa pakewuh, serba canggung tetapi mau apalagi karena sudah tidak mungkin lagi ada orang yang membantunya.
Ora Bombong
Cilakane dadi mencit, nestapanya semakin ngenes ketika sudah dalam kondisi ditinggal oleh mereka yang selama ini membantu dan bisa diperintah seenak udelnya, lalu sertamerta tidak ada lagi orang yang membesarkan hatinya, ora bombong, tidak ada lagi orang/pihak yang menyanjung, dialem-alem supaya makin maju, makin berani, dan makin sukses. Wis ta, cilaka mencit tenan; bombang ora bombong.
Dalam kondisi semacam itu, bombang ora bombong, boleh dikatakan satu-satunya harapan hanyalah tinggal di pengadilan manakala orang itu menjadi pesakitan. Mengapa? Di pengadilanlah kelak pasti ada pengacara yang mengemban tugas mbombong perkara, yaitu ngembani perkaraning liyan ing pengadilan. Pengacara itulah yang akan ngembani, yaitu berlaku sebagai pihak yang berperkara atas nama si pesakitan yang bombang ora bombong tadii.
Nestapa berkepanjangan
Tanpa bermaksud menjelek-jelekkan siapa pun, kondisi nestapa bombang ora bombong seperti itu mengingatkan bahkan mengajarkan sejumlah hal kepada siapa pun. Antara lain, pertama, bagi Anda yang saat ini sedang memangku jabatan tertentu.
Seyogianya ora usah umpak-umpakan, tidak perlu terlalu lebay sampai-sampai misalnya mengangkat asisten pribadi dalam jumah berlebih. Bahwa karena jabatan itu memungkinkan Anda mengatur sendiri berapa pun jumlah ajudan, namun kalau lebay ya namanya aji mumpung.
Kedua, bombang ora bombang sertamerta pasti akan dikaitkan dengan “siapa suka menabur angin, dia pula (pasti) akan menuai badai.” Cara berfikir post factum seperti ini bisa jadi menjadi salah satu ciri masyrakat kita, yang setelah ada kejadian, orang akan berkata: “Lha rak tenan ta?” Orang selama ini hanya “mencatat dalam hati,” dan bila kelak ada kejadian yang berkaitan dengan apa yang dicacat tadi, komentarnya “keweleh kowe” yaitu Oo.., kamu ketahuan!!!
Ketiga, bombang ora bombong semakin meyakinkan penghayatan falsafah kuna becik ketitik, ala ketara (lan kedawa-dawa); yang baik akan mengakibatkan yang (lebih) baik, sementara yang jelek akan membuahkan yang lebih jelek pula dan berkepanjangan.
Setiap peristiwa, lebih-lebih yang berakibat pada nestapa berkepanjangan, selalu membawa pesan moral sangat kuat, yakni: Semoga, ini kejadian terakhir. Tentu pertanyaannya, benarkah akan menjadi persitiwa terakhir?
Kalau benar, apa jaminannya? Jaminan dalam arti sebuah kepastian, tentulah sulit; tetapi apabila kita (manusia) mau belajar dari keledai pun; sudah terisyaratkan di sana bahwa keledai tidak akan terperosok dua kali (di tempat/kejadian yang sama).
#https://suarabaru.id/2022/08/14/nestapa-dicopot-jabatannya-bombang-ora-bombong