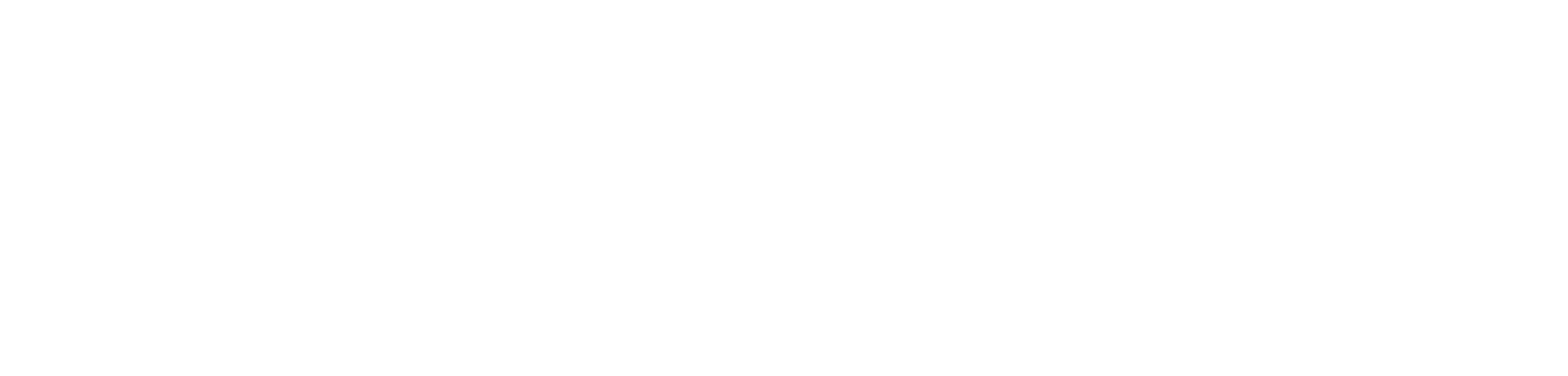[ Kompas.id – Opini – JC Tukiman Taruna – 15 November 2022]
Para politisi sejatinya adalah pengajar utama pendidikan politik masyarakat. Namun, mereka justru lebih senang berada dalam pusaran tautologi dan adverbinosis. Menyampaikan hal-hal yang serba konsep dan penuh jargon.
Siapa pengajar utama pendidikan politik masyarakat kalau bukan para politisi? Namun, amat disayangkan, terlalu sedikit (untuk tidak mengatakan nihil) politisi yang memberikan pembelajaran murni (genuine) perihal hakikat demokrasi, misalnya, kecuali sekadar menyampaikan jargon-jargon pendidikan politik masyarakat dan itu pun pasti dilatarbelakangi oleh kepentingan politik kelompok(nya).
Mengapa hal ini terjadi? Merujuk kepada kajian filosofisnya Wittgenstein, para politisi, lebih-lebih saat pemilu yang dirasa semakin ”mendekat” ini, lebih senang berada dalam pusaran tautologi dan adverbinosis.

”Salah obat”
Sejumlah politisi sangat senang mengucapkan kosakata ”salah obat”. Ini lebih-lebih ketika memberikan respons ataupun memberikan komentar atas ide, gerakan, atau gimmick sekalipun dari orang atau kelompok yang dipandangnya berlawanan. ”Salah obat, kaleee,” sambil tertawa-tawa seolah-olah kata-katanya itu tidak ada yang salah dalam konteks pendidikan politik masyarakat (PPM). Padahal, itu pembelajaran yang kurang tepat, apalagi disampaikan para politisi andal dari masing-masing partai politik. Di mana atau apa yang salah?
Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) setelah malang melintang sebagai ahli matematika, bahkan ketika mahasiswa merancang pesawat propeller, mengembangkan filsafat matematika serta logika; lalu memuncaki kajian-kajian filosofisnya kepada bahasa. Sumbangan terbesarnya justru di sini, yakni pemikiran dan telaahnya tentang betapa pentingnya bahasa: ”Harus berkembang suatu bahasa yang ideal, yang lengkap, formal, dan dapat memberi kemungkinan bagi penyelesaian problem-problem kehidupan,” ujarnya.
Maknanya, berbahasa itu seharusnya sebuah solusi, bukannya justru menimbulkan atau membawa masalah. Wittgenstein menyatakan dalam Philosophical Investigation-nya bahwa dalam berbahasa itu ada language game, tata permainan bahasa, yakni cara menggunakan bahasa pada konteks kehidupan sehari-hari setiap individu.
Bahasa sebagai wujud dari/atas jati diri seseorang. Maka, kalau ”seseorang” yang politisi andal dari masing-masing partai dan mereka menyukai ungkapan salah obat terhadap pihak yang dianggap lawan atau penentangnya; jati diri seperti apa yang diwujudkannya lewat ungkapan (bahasa) seperti itu? Pembelajaran politik macam apa yang akan disampaikannya dalam konteks PPM? Dan, mengapa saat ini orang lebih senang berbahasa seperti itu?

Tautologi dan adverbinosis
Dalam logika matematikanya, Wittgenstein memperkenalkan kata tautologi untuk menegaskan bahwa sering kali dalam kehidupan ini ada pernyataan-pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinannya. Nilai kebenaran itu selalu benar dan, untuk menopangnya, Wittgenstein membahas logika simbolik, terutama mengenai metode daftar nilai kebenaran. Kebenaran sebagaimana dapat disimak dari daftar nilai kebenaran itu disebutnya kebenaran dari logika dan matematika. Inilah kebenaran tautologis.
Dalam kehidupan sehari-hari, sayangnya, kebenaran tautologis seperti itu sering disempitkan maknanya menjadi tautologi belaka dalam arti seolah-olah ada ”satu kebenaran” lalu diulang dan diulang terus dengan harapan semua akan menjadi benar. Cara memaknai kebenaran semakin sempit saja dan siapa berseberangan (lewat pendapat berbeda, gerakan, atau bahkan gimmick pun) direspons dengan ungkapan salah obat atau sejenisnya. Di sinilah pusaran tautologi itu bermula lewat pengulangan gagasan, lewat kata-kata berlebihan, padahal penggalangan seperti itu tidak diperlukan. Bahkan, dalam konteks PPM tidak memberikan pembelajaran politik apa pun kepada masyarakat.
Politisi, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masih banyak pihak lainnya, dalam kata-kata (baca: dalam berbahasa) setiap hari semata-mata hanya penuh dengan kata-kata konsep, jargon, bahkan perintah belaka.
Contoh lain tautologi dapat disimak dari penggalan pidato banyak tokoh seperti ini: ”Saudara-saudara, mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa adalah salah satu cara terbaik agar kita tenang, damai, tenteram, dan merasa nyaman dalam hidup ini.”
Siapa sering mengulang-ulang kalimat seperti itu? Siapa saja, karena memang kalimat itu bukan hak paten seorang tokoh agama saja. Namun, adakah pengulangan atas kalimat itu bermakna bagi masyarakat? Itu pengulangan tautologis belaka, apalagi di dalam kalimat itu pun ada klausa yang memiliki kesamaan makna antara tenang, damai, tenteram, dan nyaman. Dan yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat, pasti: ”Bagaimana itu dapat dilakukan atau dapat terjadi?”
Mengulang-ulang konsep secara tautologis, ini dilakukan oleh amat banyak pihak, menimbulkan gejala adverbinosis dalam kehidupan sehari-hari kita; yakni gejala kehilangan kata kerja. Politisi, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masih banyak pihak lainnya, dalam kata-kata (baca: dalam berbahasa) setiap hari semata-mata hanya penuh dengan kata-kata konsep, jargon, bahkan perintah belaka. Serba kata benda.
Politisi, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat terjangkit adverbinosis karena mengira bahwa kebenaran tautologisnya Wittgenstein itu ada di dalam kata benda (serba konsep penuh jargon). Padahal, yang benar justru berada di dalam kata kerja karena di situlah ada solusi atas berbagai permasalahan. Kata kerja yang benar tentulah kata kerja yang terkait langsung dengan how to.
Mengalami langsung
Gejala semakin kehilangan ungkapan-ungkapan kata kerja, adverbinosis, rupanya bermula dari kecenderungan orang yang suka mengulang-ulang konsep, atau bahkan menggunakan kata-kata tertentu secara berlebihan, padahal hal itu tidak diperlukan sebenarnya. Dengan kata lain, ada kemungkinan gejala itu dikarenakan semakin berkurangnya kesempatan orang mengalami secara langsung apa saja. Ungkapan kekinian mengatakan: ”Ah, kurang blusukan, itu.”
Bicara tentang bagaimana blusukan, yaitu memperbanyak kata kerja karena mengalami secara langsung banyak hal; kisah hidup masa mudanya Wittgenstein dapatlah kiranya memberi inspirasi. Ia lahir dan hidup di Austria, tetapi sering bepergian ke Norwegia, bahkan di sana ia pernah tinggal beberapa lama di sebuah gubuk yang dibuatnya sendiri. Kegiatannya di situ, menulis.
Pada waktu Perang Dunia I, Wittgenstein menjadi tentara, bahkan pernah ditawan/dipenjara (1918) di Italia. Dalam penjara, kegiatan menulisnya semakin terasah sepenuh waktu. Sepulang dari tawanan, ia menolak harta warisan orangtuanya. Untuk menghidupi diri, ia bekerja sebagai guru sekolah dasar hingga tahun 1926. Dalam masa sebagai guru ini, ia menyusun kamus untuk sekolah dasar; tetapi lalu keluar dari pekerjaannya sebagai guru dan menjadi tukang kebun di sebuah biara Katolik.
JC Tukiman Taruna, Pengamat Pendidikan; Pengajar Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata, Semarang
Sumber : https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/14/salah-obat-politisi-dalam-pusaran-konsep-penuh-jargon