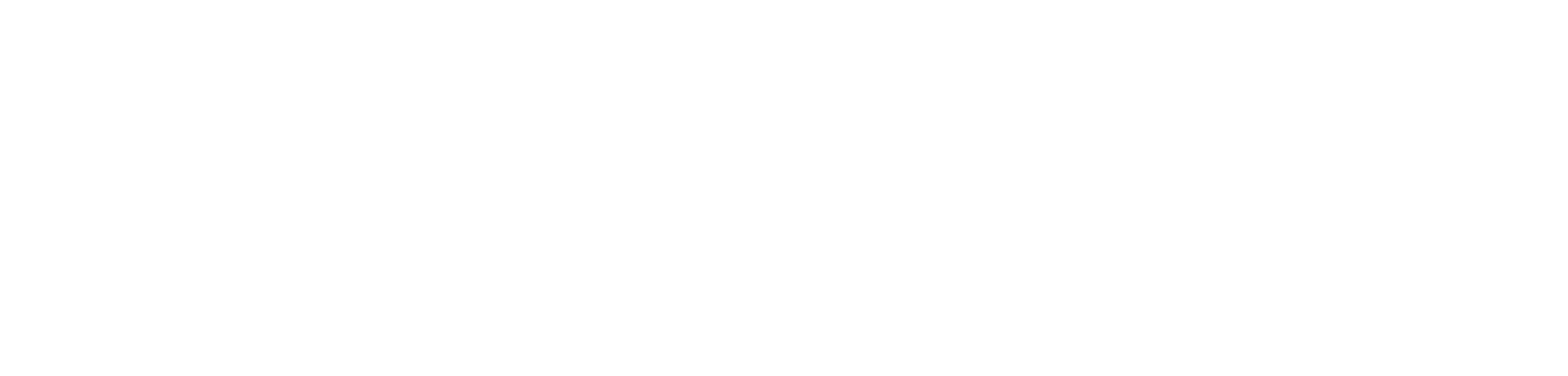Oleh: Budi Widianarko, Guru Besar Unika Soegijapranata, Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang
Dalam proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dua pertiga populasi dunia akan tinggal di kota. Sistem pangan kota yang berkelanjutan adalah sebuah ideal baru yang ingin dicapai oleh kota-kota dunia.
Akibat perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, ”hantu” krisis pangan global benar-benar menampakkan wujudnya.
Harga pangan melonjak sehingga memunculkan kekhawatiran serius, khususnya di negara-negara yang mengandalkan kecukupan pangannya dari impor. Sistem pangan di negara-negara tersebut mulai goyah dan memerlukan topangan baru untuk bisa kembali tegak.
Alih-alih menanti rampungnya perang dan berbagai upaya diplomasi untuk normalisasi alur pasok bahan pangan dan sarana produksi pendukungnya—seperti pupuk—diperlukan berbagai terobosan strategis dan gercep (gerak cepat). Salah satunya melalui transformasi sistem pangan kota.
Dalam proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dua pertiga populasi dunia akan tinggal di kota. Meski hanya menempati 2-3 persen luas permukaan bumi, dengan gaya hidup dan praktik konsumsi warganya, kota memonopoli tiga perempat atau 75 persen sumber daya alam (SDA) dan menyumbang lebih dari 70 persen emisi gas rumah kaca global (UNEP, 2017; Wei dkk, 2021).
Hal ini mendorong perlunya transformasi sistem pangan kota sesegera mungkin. Sistem pangan mencakup alur produksi pangan—dari lahan ke meja makan—beserta segenap pelaku, kelembagaan dan infrastruktur pendukung serta dampaknya terhadap tiga aspek keberlanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Mengapa kota?
Kota adalah bagian dari masalah dan sekaligus solusi bagi tantangan sistem pangan. Kawasan perkotaan yang kian meluas sering kali berasosiasi dengan meningkatnya konsumsi sumber daya dan produksi limbah yang memberikan tekanan terhadap ekosistem dan alur pasok pangan.
Pertumbuhan populasi kota telah memicu terkonsentrasinya penduduk di kawasan-kawasan rentan (vulnerable). Kota-kota menjadi sumber masalah bagi sistem sosial dan ekosistem, dan dampak negatifnya cenderung terus meningkat seiring laju urbanisasi dan perubahan. Namun, pada saat yang sama, kota juga merupakan bagian dari solusi.
Idealnya, kota bukan hanya pelahap pangan, tetapi juga harus mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri. Sebagai konsekuensinya, sudah saatnya melibatkan isu-isu pangan dalam perencanaan kota. UNEP (2017) menyebut kemampuan kota dalam menyediakan sebagian pangannya sendiri dan pelibatan pangan dalam rencana kota adalah esensi dari transformasi sistem pangan kota.

Kepadatan dan kedekatan jarak (proximity) di dalam sebuah kota sebenarnya mereduksi biaya ekonomi dan lingkungan dalam penyediaan infrastruktur dan jasa untuk produksi pangan. Selain itu, kota juga memiliki kapasitas kelembagaan dan teknikal yang signifikan untuk menghadapi masalah lingkungan, termasuk masalah pangan.
Yang juga tidak boleh dilupakan, kota sudah selayaknya merupakan pusat inovasi. Bagaimana tidak? Bukankah perguruan tinggi dan lembaga penelitian terkonsentrasi di kota?
Transformasi
Sistem pangan kota yang berkelanjutan (sustainable urban food system) adalah sebuah ideal baru yang ingin dicapai oleh kota-kota dunia. Tekanan sistem pangan yang terus meningkat terhadap planet Bumi telah semakin dikenali, bukan saja oleh kalangan ilmiah, melainkan juga oleh para pengambil kebijakan kota.
Salah satu prakarsa global untuk mewujudkan sistem pangan berkelanjutan adalah Pakta Milan (Milan Urban Food Policy Pact) yang diprakarsai oleh kota Milan di Italia. Hingga pertengahan tahun 2022 sudah 225 kota di dunia yang menjadi anggota dari pakta ini, termasuk lima kota di Indonesia. Tercatat sudah ada 370 praktik baik sistem pangan kota yang terdokumentasi di dalam Pakta Milan.
Seperti mengukuhkan kota sebagai pusat kreativitas dan inovasi, saat ini sudah banyak kota yang telah memulai transformasi sistem pangannya melalui berbagai prakarsa inovatif yang mendukung prinsip keberlanjutan.
Menariknya, prakarsa-prakarsa itu tidak hanya dimotori oleh pemerintah, tetapi juga digagas dan dikembangkan oleh warga. Prakarsa inovatif itu juga telah bersemi dan berkembang di kota-kota belahan bumi utara ataupun selatan. Pada intinya prakarsa-prakarsa itu menawarkan berbagai cara baru untuk menyediakan pangan bagi kota.
Salah satu kota yang mau tak mau harus mentransformasi sistem pangannya adalah Singapura. Negara kota itu punya sasaran yang ambisius, memenuhi 30 persen kebutuhan pangannya sendiri pada 2030 (30 by 30 Plan), dan menggenapi sisanya dengan impor dari 170 negara dan bertani di luar negeri.
Untuk mencapainya, Singapura memerlukan pendekatan holistik dan berjangka panjang dalam tata ruang, teknologi pertanian-pangan (agrifood) dan pengembangan tenaga ahli pertanian lokal (agrispecialists).

Apa yang dilakukan Singapura tentu bisa dilakukan kota-kota di Nusantara ini. Bahkan harus menjadi keniscayaan bahwa sebagian besar kota kita lebih unggul. Keunggulan itu ditopang oleh ketersediaan lahan (termasuk pekarangan), keberadaan lembaga pendidikan menengah (SMK) dan pendidikan tinggi di bidang pertanian-pangan, serta budaya pertanian yang masih kental karena masih kuatnya relasi kota-desa.
Di sisi lain, pertanian kota (urban farming) mulai berkembang di kota-kota kita dan telah menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk kelompok milenial. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengangkat kegiatan pertanian kota jadi lebih dari sekadar ”riasan” (gimmick) kota yang hanya bertumpu pada hobi warga.
Transformasi menuju sistem pangan kota yang berkelanjutan akan memiliki dampak multidimensi. Secara ekonomi: penguatan ketahanan pangan lokal akan dengan sendirinya meningkatkan ketahanan ekonomi kota.
Secara sosial: kemampuan produksi pangan lokal yang melibatkan warga dari beragam status sosial-ekonomi akan membentuk rantai pasok lokal yang inklusif. Secara lingkungan: semakin lokal rantai pasok pangan tentu saja semakin rendah jejak lingkungannya—seperti jejak air dan jejak karbon—begitu pula sirkularitas juga akan terbentuk ketika limbah pangan dilibatkan sebagai sumber daya ”baru” dalam sistem pangan.
Salah satu kota yang sedang mendapat fasilitasi untuk menjalankan transformasi sistem pangannya adalah Semarang. Di kota ini sedang berlangsung proyek Sustainable, Healthy, Inclusive Food System Transformation (SHIFT) Bappenas-UNEP yang dilaksanakan Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari (WAIBI) dan Unika Soegijapranata.
Semarang adalah sebuah metropolitan yang unik karena watak agrarisnya masih kuat. Hampir 32 persen dari kota seluas 373,7 kilometer persegi itu berupa lahan pertanian, dengan luas sawah lebih dari 22 kilometer persegi dan sekitar 16 kilometer persegi telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Tidak mengherankan jika tahun lalu (2021) Semarang mampu memenuhi 15 persen dari kebutuhan berasnya sendiri, selain daging ayam (67 persen), telur ayam (54 persen), dan berbagai buah serta sayuran.
Apa yang ada di Semarang tentu dijumpai pula di banyak kota negeri ini. Untuk memastikan bahwa kota-kota kita dapat menjadi penyumbang pangan diperlukan sebuah visi sistem pangan kota yang tepat dan relevan dengan kondisi setiap kota. Perumusan visi itu mesti melibatkan segenap pemangku kepentingan pertanian-pangan di tiap-tiap kota karena pada gilirannya merekalah yang akan mewujudkan visi ini.
Kalau Singapura ”berani” punya visi 30-30, kota-kota kita tidak boleh kalah.

#Kompas 15 Juli 2022, hal. 6
https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/14/kota-penyumbang-pangan